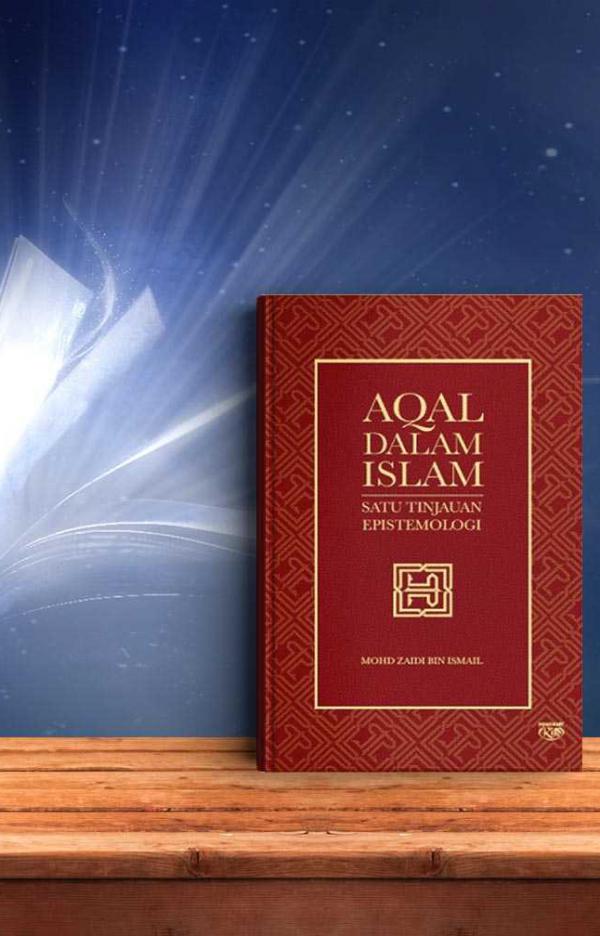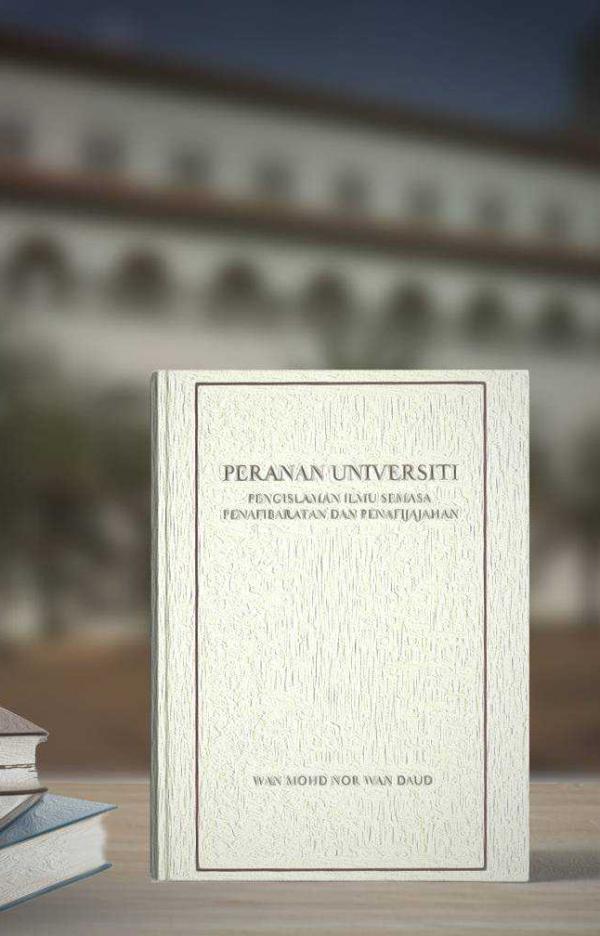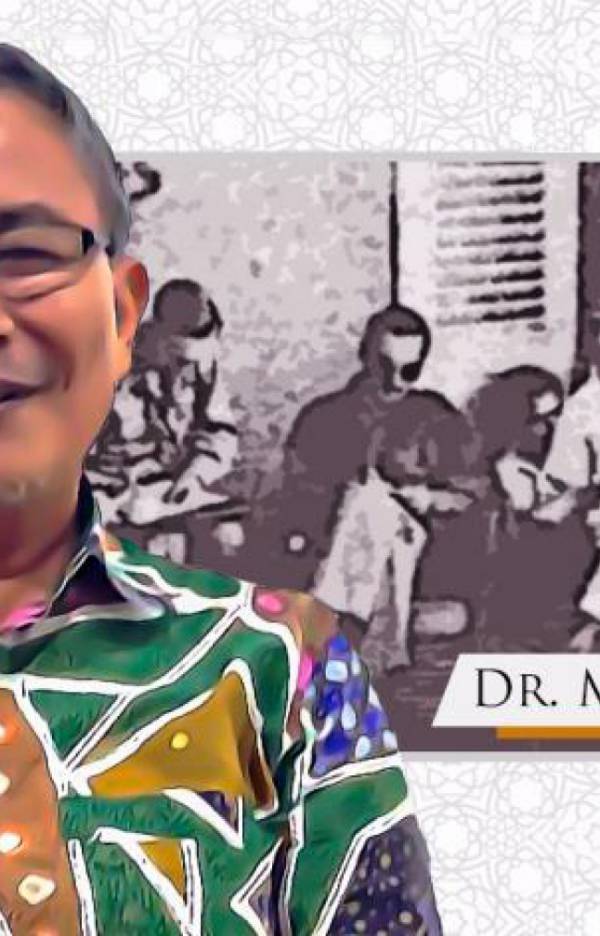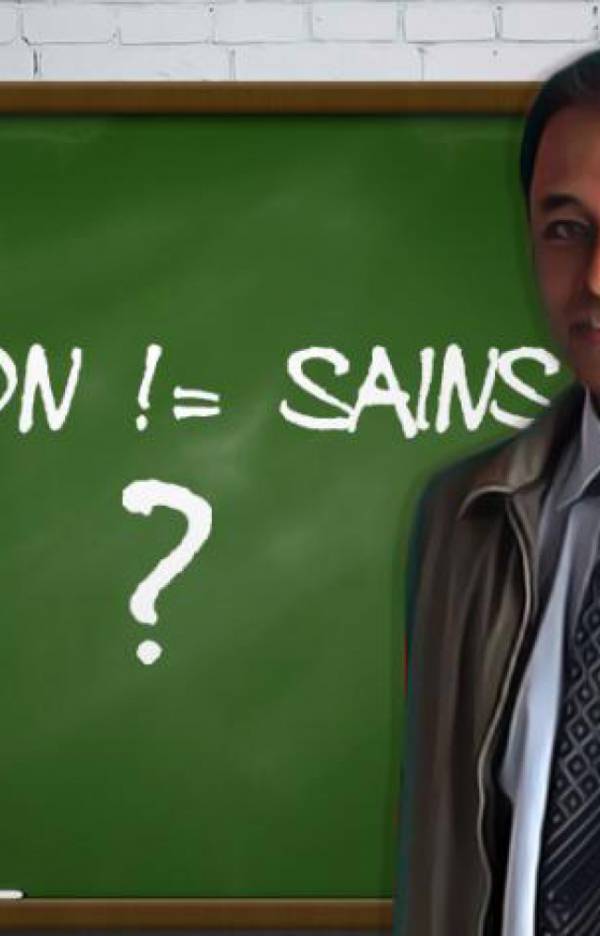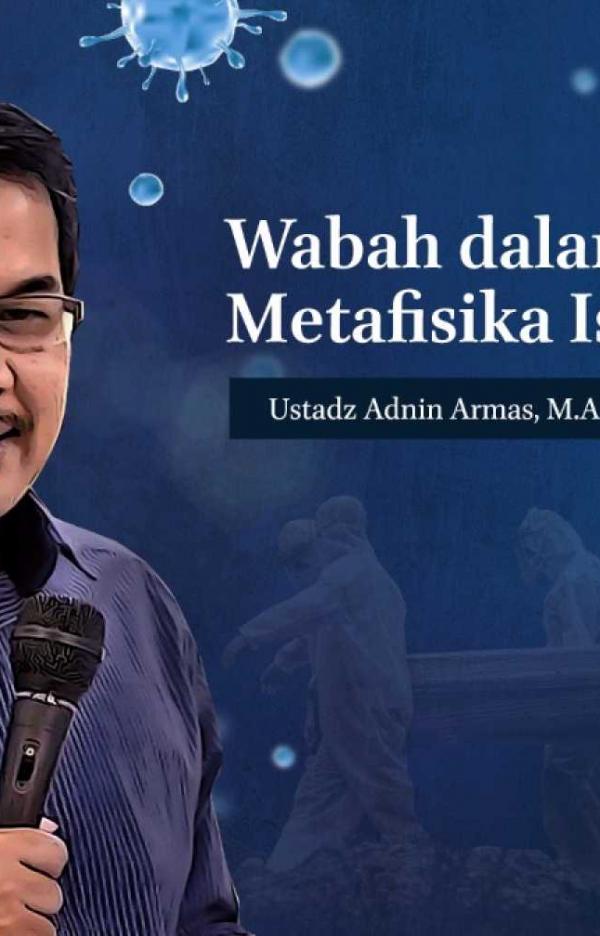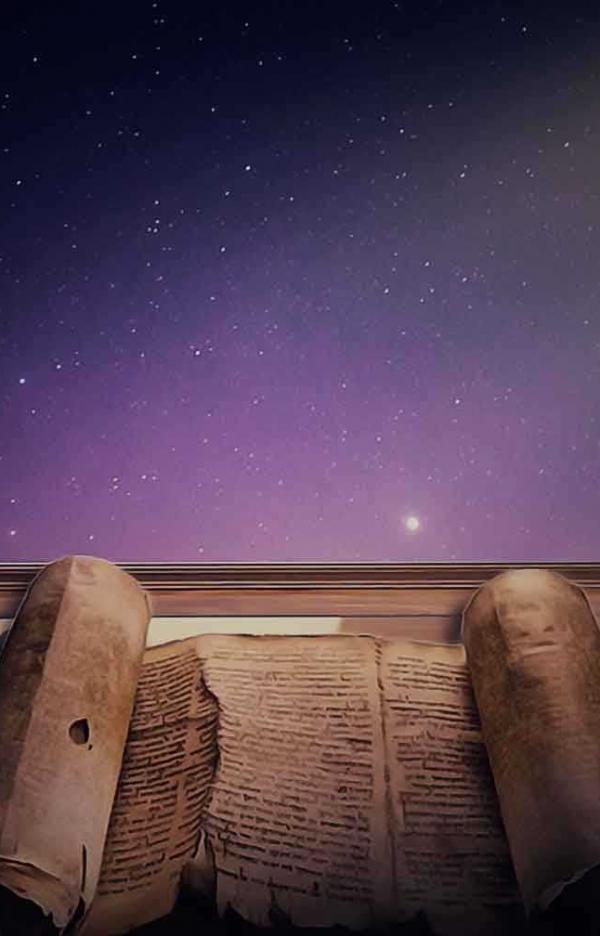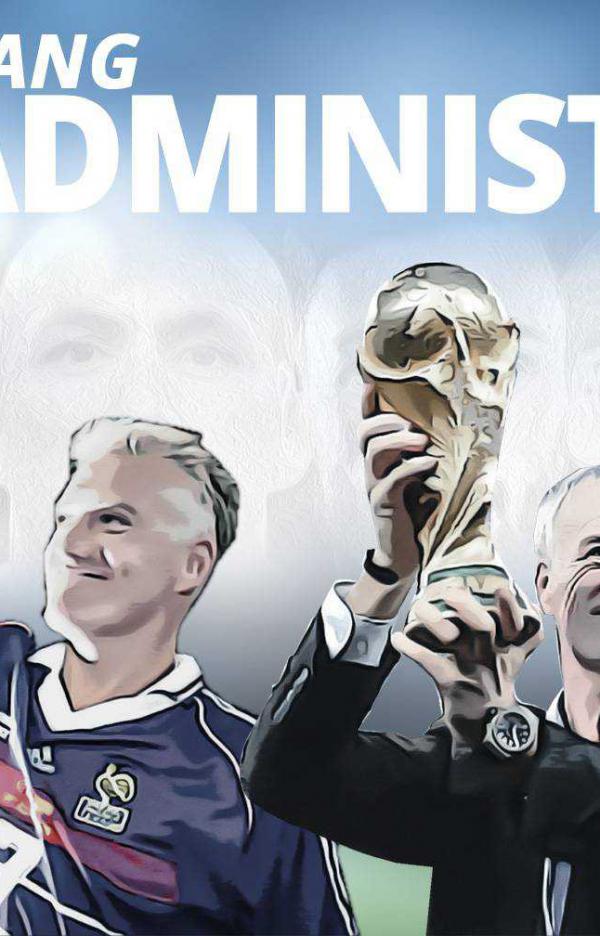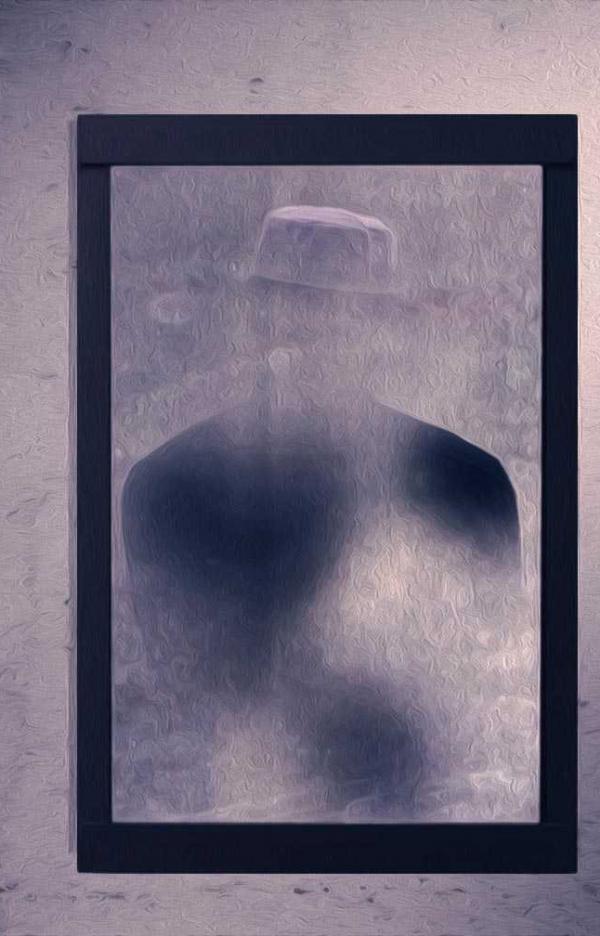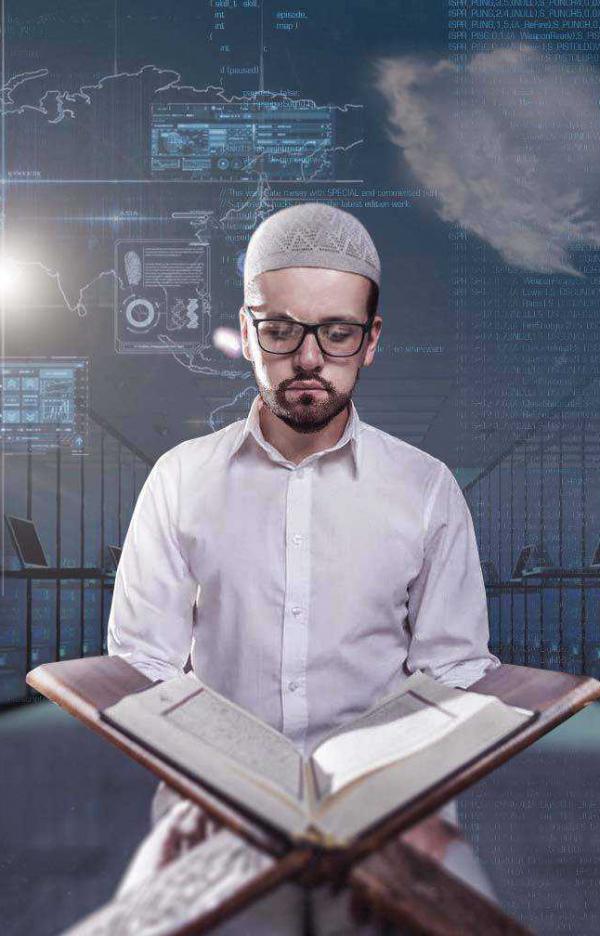Umum diketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negeri sekaligus sebuah kebudayaan yang terdiri dari ratus-ratus suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri. Apa itu kebudayaan Indonesia telah lama menjadi perbincangan. Apakah kebudayaan Indonesia itu merupakan kumpulan, hasil perasan, atau campuran dari macam-macam kebudayaan daerah? Ataukah, suatu unsur baru yang merupakan bagian dari kebudayaan dunia?
Tulisan ini tidak berminat menjawab soal-soal sulit tersebut dalam ritmis ilmiah; tidak akan menampilkan rupa-rupa makna kebudayaan dari berbagai kamus dan pendapat ahli; dan tidak pula berhasrat untuk merumuskan dengan saksama apa itu kebudayaan Indonesia. Di dalam tulisan ini hanya akan ditampilkan beberapa soal sehari-hari yang pernah terlalui dalam hidup penulisnya. Boleh jadi, soal sehari-hari itu ada kaitannya dengan masalah kebudayaan dimaksud.
Pada masa sekolah dasar dulu, di daerah Bandung Timur, saya dan kawan-kawan sebaya biasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Bukan kami tak bisa berbahasa Sunda, tetapi menggunakan bahasa Indonesia rasanya lebih hebat, lebih menasional, lebih keren, dan mungkin tidak kampungan. Bukan bahasa Indonesia yang baik sepertinya, tetapi bahasa Indonesia yang ditampilkan di televisi. Perasaan ini menjangkiti masa kanak-kanak saya: menggunakan bahasa Indonesia rasanya lebih terhormat dan maju sementara berbahasa Sunda kadang malah menjadi ciri kekasaran. Suatu pandangan yang saya sesali kini.
Setelah agak dewasa, kawan-kawan sekitar saya biasa berbicara keinggris-inggrisan. Sepertinya, menggunakan bahasa Inggris lebih maju daripada menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Di masa dewasa, saya amat menyadari bahwa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ialah sama-sama bahasa yang mengandung keluhuran khas masing-masing. Yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain.
Di masa muda pula saya lebih bangga menggunakan sepatu daripada terompah. Mengikuti gaya anak-anak Jakarta yang dipropagandakan sinetron dan iklan di televisi. Gaya rambut, cara berpakaian, dan pola ungkapan kami di daerah berporos pada sinetron, iklan, dan film. Mal ialah tempat main yang bergengsi, pergi makan atau berbelanja di sana mencirikan taraf hidup yang tinggi. Kami mengunjunginya paling tidak setahun sekali menjelang Lebaran. Namun, perasaan naik derajat itu tidak pernah kami rasakan ketika pergi ke pasar untuk membeli ikan atau kangkung.
Sepanjang masa usia sekolah dasar, yang saya fahami sebagai pakaian nasional ialah batik dan jas-dasi yang dipakai Pak Harto. Sementara, pakaian daerah hanya saya lihat di buku Atlas Nasional, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap, dan upacara pernikahan. Dalam keseharian, saya tidak melihat orang-orang berpakaian daerah atau berpakaian nasional. Dalam keseharian orang-orang berpakaian biasa-biasa saja.
Maka, saya simpulkan bahwa pakaian adat ialah pakaian yang dipakai pengantin ketika resepsi perkawinan sementara pakaian nasional ialah pakaian yang dipakai mempelai pria ketika mengucapkan ijab-kabul. Batik dan jas-dasilah yang saya cerap sebagai pakaian nasional. Sinjang, ulos, songket, atau koteka bukan merupakan pakaian nasional, itu pakaian daerah.
Lagu nasional yang saya fahami ialah musik-musik wajib yang diajarkan di sekolah, mulai dari Indonesia Raya sampai Gugur Bunga. Sementara, Manuk Dadali atau Cing Cang Keling ialah musik daerah. Belakangan saya baru tahu bahwa musik nasional itu yang nadanya seperti orang barat (do-re-mi-fa-sol-la-si-do) sementara musik daerah Sunda itu yang da-mi-na-ti-la-da. Mana yang lebih keren di antara keduanya? Tentu saja yang tampil di MTV atau Delta.
Dari sekolah dasar saya sudah diajarkan Pancasila, bahkan diwajibkan untuk menghafal butir-butirnya yang banyak itu. Namun sampai kini, saya tidak bisa menalar persoalan-persoalan di atas dengan Pancasila itu. Mengapa berbahasa Inggris rasanya lebih keren dari bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia rasanya lebih mantep daripada bahasa daerah. Bagaimana lagu daerah dan lagu nasional di pandang dari sudut-sudut intipan Pancasila yang katanya harga mati itu? Dan, mengapa John Lennon atau Justin Bieber terlihat lebih mulia dari Rhoma Irama atau Ki Mantus?
Saya merasa segala sesuatu yang berbau daerah itu kerap dipandang lebih terbelakang daripada yang nasional. Dan, yang nasional itu lebih terbelakang dari yang internasional. Apakah ini semacam inferority complex bertingkat nan absurd dari kebudayaan dan jiwa kita?
Saya terkenang beberapa novel Balai Pustaka yang masyhur dan melegenda. Sebagian ceritanya selalu menampilkan orang daerah atau kebiasaan daerah yang membelenggu bahkan menindas kemanusiaan, berbanding orang dengan sekolah Belanda yang digambarkan lebih dapat memahami manusia dan berperadaban. Dalam Kasih Tak Sampai (Siti Nurbaya), Syamsul Bahri yang bersekolah Belanda digambarkan begitu rasional, berani, dan cerdas. Sosok itu berbanding dengan Datuk Maringgih yang licik, kolot, dan tak mampu mengendalikan nafsunya. Perbandingan yang sama dapat kita lihat dalam Sengsara Membawa Nikmat, sosok Midun yang akhirnya menjadi pegawai Belanda amat beradab dibanding Ungku Muda Kacak yang licik, bodoh, dan korup.
Boleh jadi, pandangan daerah dan nasional yang sumbang begitu berasal dari jiwa kolonial yang diam-diam merembes ke dalam jiwa bangsa kita. Pandangan soal apa itu kemajuan, kemanusiaan, dan keberadaban kita amat diwarnai struktur daerah-nasional-internasional yang sebenarnya amat feodalistis. Pada akhirnya kemerdekaan tidak melepaskan kita dari budaya feodal melainkan memindahkan kita dari budaya feodal raja-raja menuju feodalisme baru yang didukung penyebaran penyakit kompleks-rendah diri. Ini bukan sebuah kesimpulan melainkan hanya sebuah kebolehjadiaan yang tersirat di pinggiran, di obrolan warung kopi. Boleh diabaikan, boleh juga difikirkan dalam-dalam.