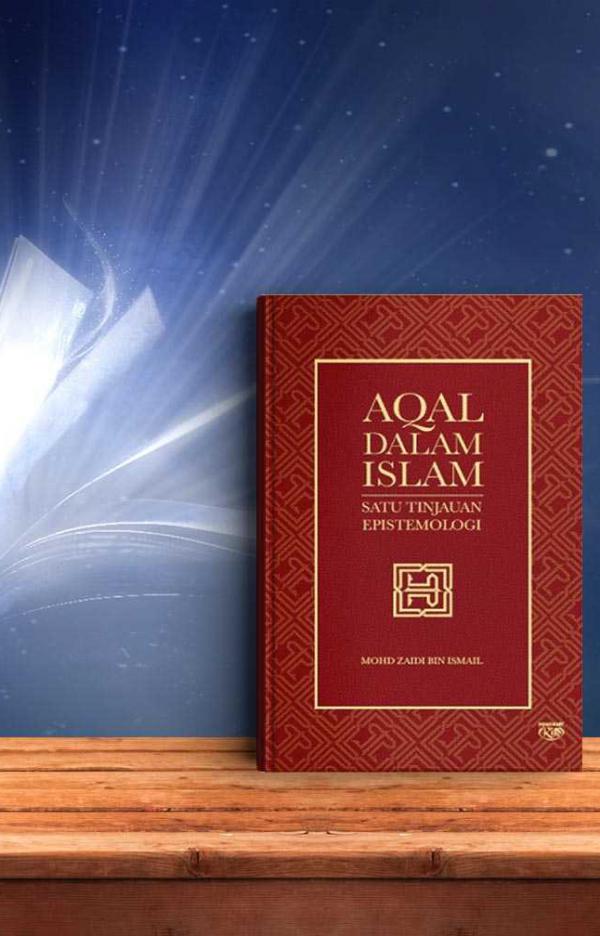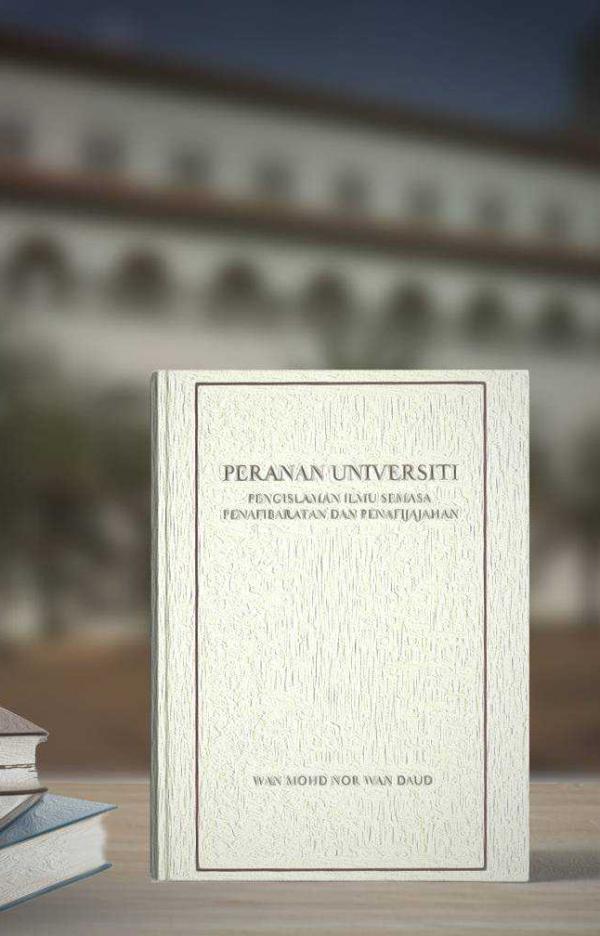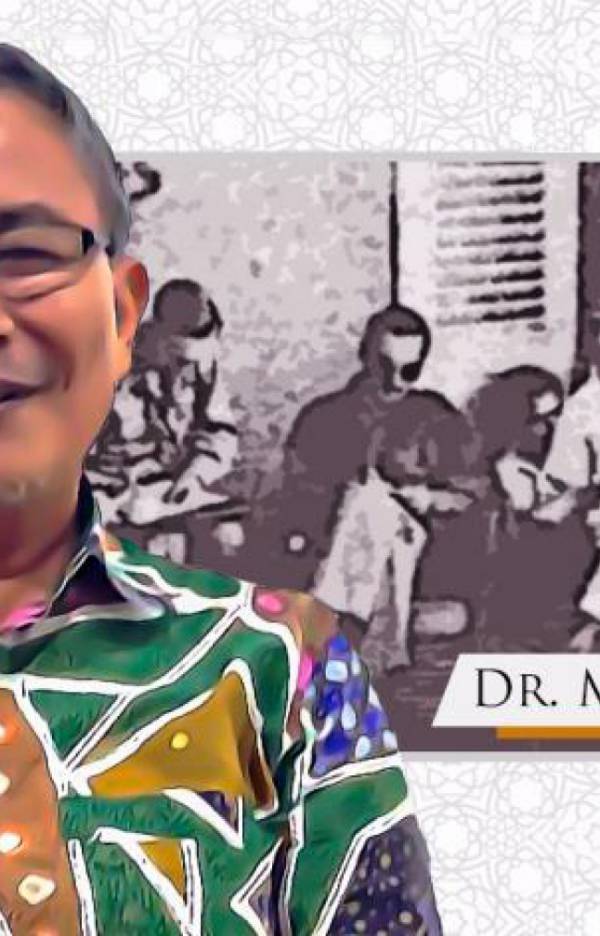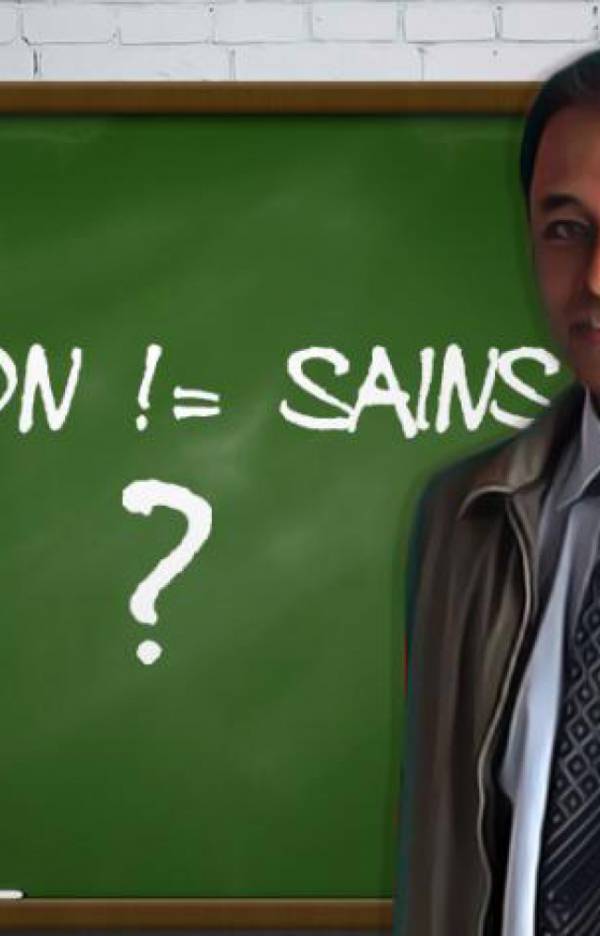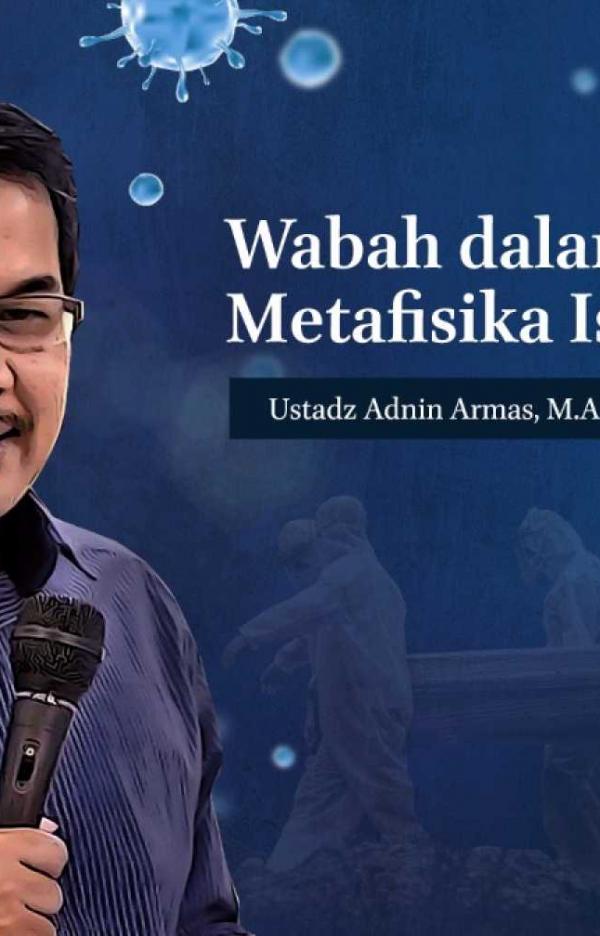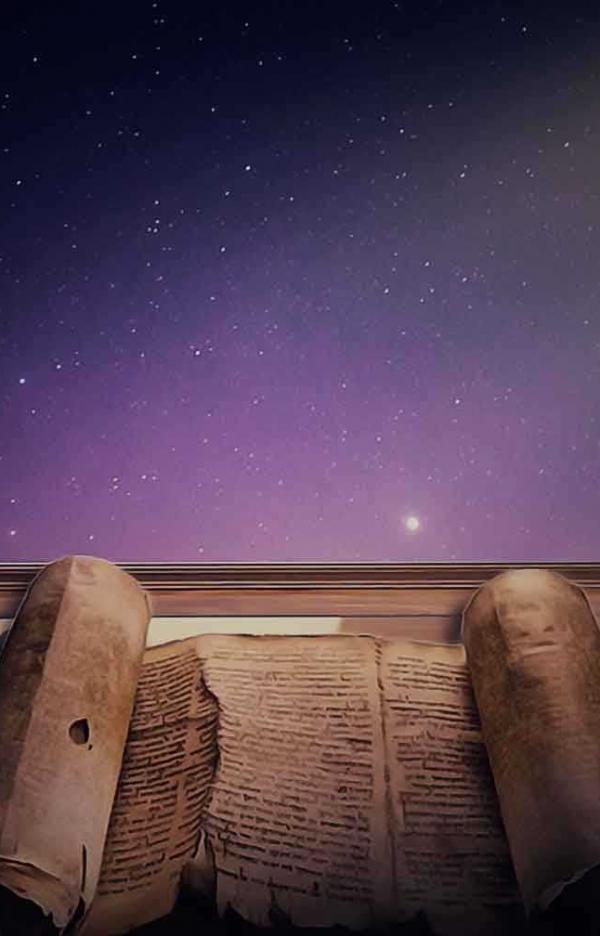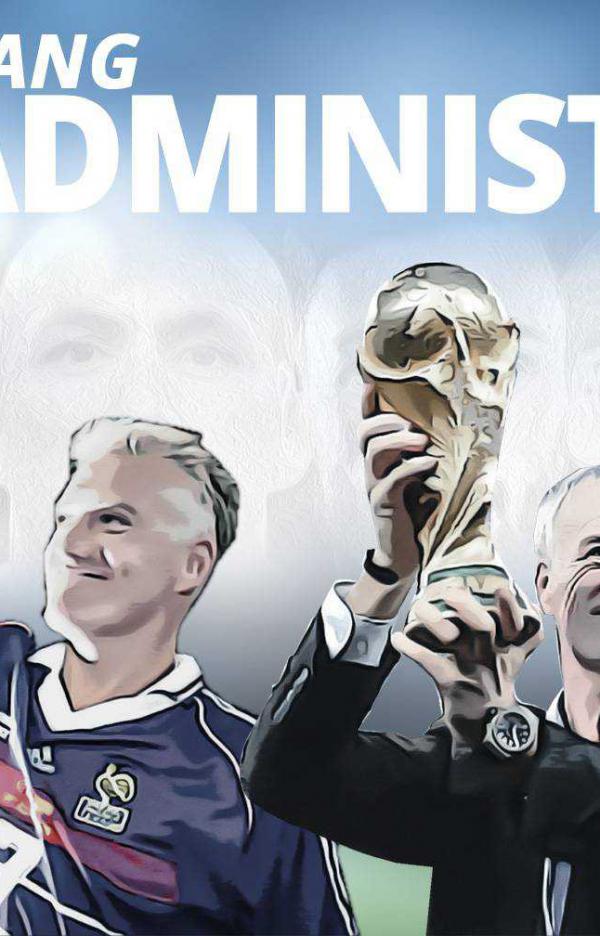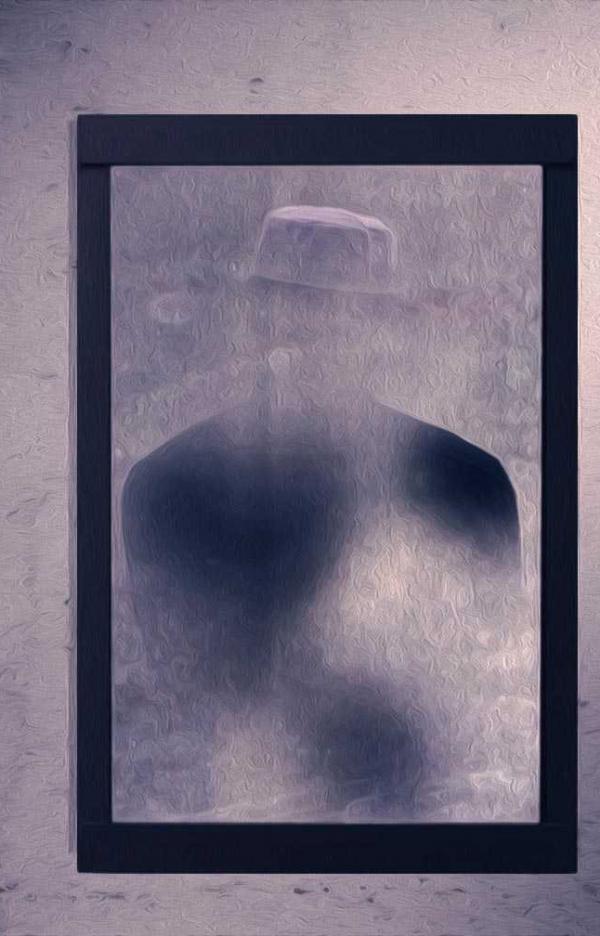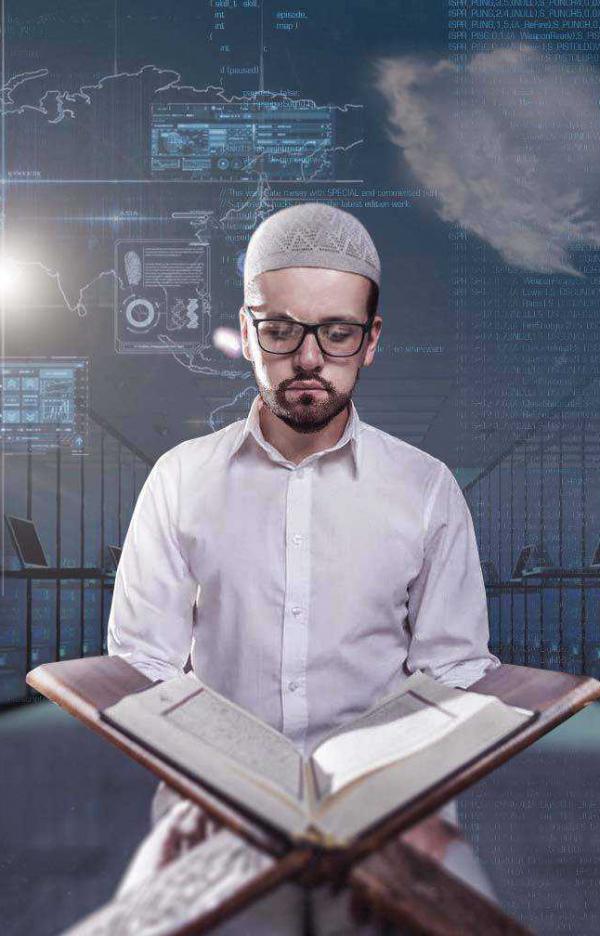Politikdan agama merupakan dua hal yang hadir secara nyata dalam kehidupan manusia.Kebudayaan manusia tak dapat dipisahkan dari politik dan apalagi dari agama.Beragama ialah tindakan khas manusia sebagaimana juga politik yang hanyadilakukan oleh manusia. Manusia ialah makhluk yang beragama dan jugaberpolitik. Keduanya hal yang merupakan bagian langsung dari peradaban manusia.Hubungan antara kedua hal ini dapat dilihat dari beragam cara penelaahan. Tentusaja di balik setiap cara penelaahan terdapat suatu falsafah atau jugapandangan hidup (worldview).
Setidaknyaada dua pandangan mengenai hubungan agama dan politik. Kalangan sekulerberpandangan bahwa politik harus dipisahkan dari agama dan menolak “membawaâ€agama ke ranah politik. Sementara, di sisi yang lain terdapat kaum yangberanggapan bahwa politik ialah bagian dari agama. Perbincangan mengenai halini telah lama berlangsung. Hingga hari ini, kedua pihak selalu berusahamembangun hujah bagi pendapat mereka masing-masing.
Di duniaBarat, perhubungan antara agama dan politik berlangsung tegang, bahkanbertentangan. Agama (Kristen) didudukkan sebagai tertuduh dalam kronikkelahiran modernisme di dunia Barat. Bagi manusia Barat, agama adalahpenghambat kemajuan dan kebebasan berpikir. Keyakinan terhadap agama telahmenghalangi manusia menjelajah alam dan batas-batas kemanusiaan.
AugusteComte pada pertengahan abad ke-19 telah melihat bahwa masyarakat Barat akanterus berkembang ke arah modern. Hal itu ditandai dengan makin ditinggalkannyapandangan-pandangan keagamaan terhadap kenyataan. Masyarakat Barat pada era itutelah gandrung untuk melihat kenyataan berdasarkan kepada sains, bukan teologi.Akal kemudian lebih dipercayai memberikan jalan kepada kebenaran dibandingkanwahyu.
Comtemengatakan:
“When theheart is no longer crushed by theological dogmas, or hardened by metaphysicaltheories, we soon discover that the real happiness, whether public or private,consists in the highest possible development of the social instincts. (Comte,1865 [2009], hlm 237).
[Ketikajiwa kita tidak lagi dihancurkan oleh dogma-dogma teologi atau dibekukan olehteori-teori metafisika, kita akan segera mendapati bahwa kebahagiaan sejati,baik di ranah umum ataupun ranah pribadi, terdapat di dalam perkembangantertinggi yang mungkin dicapai oleh insting sosial].
Agamamemang tidak disingkirkan dari keseluruhan kehidupan. Meski ateisme menjadipandangan yang mengumum pada masa puncak modernisme, agama tetap diberi ruanguntuk hadir. Namun, agama tidak diperkenankan hadir di ruang-ruang umum. Agamadidudukkan di wilayah keyakinan yang terpisah dari pengetahuan. Keyakinan tidakmemiliki hubungan apa-apa dengan pengetahuan. Keduanya terpisah, bahkan seringdianggap bertentangan. Pun keyakinan tak diperkenankan hadir dalam ruang-ruangumum. Kehidupan sosial dan politik dianggap sebagai peristiwa manusiawi belaka.
Agamabisa juga menjadi bagian dari nilai-nilai politik, asal bisa menyambung dengankeyakinan politik sekuler. Jurgen Habermas, misalnya, memandang bahwa agamabisa memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan politik. Hal ini menjadiwajar karena nilai-nilai yang hidup di dunia ini, khususnya politik, tidaksebatas nilai-nilai sekuler. Nilai agama juga digunakan oleh sebagian kalanganmanusia di dunia saat ini. Habermas menyadari hal itu. Dalam pandangannya,dunia saat ini adalah dunia yang post-sekuler.Hal ini dapat dilihat dari tulisannya: “Religion and the Public Sphere†(European Journal of Philosophy, vol V,2006: 33).
Akantetapi, Habermas melihat bahwa agama menjadi salah satu sumber nilai dalamkehidupan politiknya (Hardiman, 2009). Dalam diskusi publik soal politik, agamaharus dikemas ke dalam bahasa yang dipahami bersama (ground) dalam komunikasi rasional, sebab cara pandang agama satudengan yang lainnya berbeda dan memiliki konsep-konsep kunci yang berbeda(Hardiman, 2009:158). Untuk itu, agama harus dapat diperbincangkan denganbahasa (konsep) yang bisa dipahami khalayak ramai, peserta semesta wicara. Olehkarena itu, agama kemudian tidak lagi menjadi sesuatu yang sepenuhnya sakral.Agama telah disempitkan menjadi objek alam yang dapat diperbincangkan.
Orang-orangBarat pada masa modern secara tegas menghilangkan nilai-nilai suci dan wibawaagama dari politik (desacralization ofpolitics). Bagi mereka tidak ada pengesahan agama pada kekuasaan danotoritas politik apa pun. Politik dipandang sebagai peristiwa manusiawi belakayang tak bersangkut paut dengan keruhanian jenis apa pun. Manusia tidakmemiliki perangkat apa pun untuk meraih pengesahan dari Tuhan (atau hal-hallain di luar manusia) atas kekuasaannya. Kekuasaan dan pengaturan masyarakatdianggap murni urusan manusia. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengelolaperpolitikan dengan apa yang ada pada dirinya; dengan daya-daya akliah dan dayamanusiawinya yang (dianggap) tak pernah terhubung dengan sesuatu apa pun diluar sana (lihat al-Attas, 2010, hlm 20—21).
Kekuasaanseorang raja atau seorang presiden dipandang murni sebagai proses kemanusiaan.Manusialah yang menjadikan manusia lainnya menjadi raja atau presiden melaluiprosedur-prosedur manusiawi. Tidak ada kekuatan lain yang menjadikan seseorangitu raja, presiden, atau rakyat biasa. Kedudukan setiap orang dipandang sebagaisebuah peristiwa yang murni manusiawi. Dan manusia dipandang tidak memiliki perangkatapa pun untuk mendapatkan pengesahan dari Tuhan atas kuasa dan kepemimpinanyang ia dapatkan.
Agamaterkadang diperkenankan hadir dalam politik, tetapi hanya sebagai etika belaka.Agama diperkenankan memandu sikap dan moral umat penganutnya dalam berpolitik.Namun, ia tak diperkenankan untuk menjadi hukum formal dan landasan politikdalam sebuah negara. Ini tentu saja merupakan sebuah tindakan yang reduktifterhadap makna agama.
Islam—sebagaisebuah agama dan tentu saja sebagai sebuah tata falsafah—memiliki cara pandangyang khas terhadap persoalan ini. Di dalam Islam, kekuasaan dan kewibawaanpolitik mestilah dibersihkan dari segala pandangan-pandangan supranatural.Politik harus dibebaskan dari segala belenggu mistik. Tidak ada satu entitaspun, tak ada sesuatu kekuatan pun tempat bergantung sebuah kekuasaan kecualikepada Allah SWT. Tujuan akhir dari politik haruslah Allah SWT. Politik tidakboleh dilaksanakan dengan tujuan-tujuan duniawi dan kebendaan belaka.
Bagisetiap Muslim, baik sebagai pribadi maupun masyarakat (sebagai suatu ummah), pengesahan agama apa pun atassebuah kekuasaan akan ditolak. Sebuah negara dan sebuah pemerintahan hanyadapat diikuti hanya dan hanya apabila mengikuti aturan-aturan Allah danRasulnya. Seorang Muslim tidak perlu memberikan ketaatan dan kesetiaan kepadaraja atau negeri, sebab kesetiaan dan ketaatan tertinggi hanya layak diberikankepada Allah SWT dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Salla’LlÄhu ‘alayhiwasallam. Ketaatan, sumpah setia, dan kesetiaan seorang Muslim sesungguhnyahanya bagi Allah SWT dan kepada Nabi-Nya, dan tidak menyertakan yang selain-Nya(lihat al-Attas, 2010, hlm 38—39).
Dengandemikian, bagi seorang Muslim berpolitik harus terbebas dari belenggukekuasaan-kekuasaan mistik dan sekaligus mesti bersih dari penghambaan manusiaatas manusia. Tempat bergantung dan tujuan akhir seorang Muslim dalamberpolitik hanyalah Allah SWT. Politik pada akhirnya juga pembebasan manusiadari belenggu-belenggu mistik dan takhayul sekaligus pembebasan manusia daripenguasaan (atau lebih jauh penindasan) manusia lainnya.
Tanpapenggantungan kepada Allah SWT, politik akan dikerubungi tujuan-tujuanduniawi-kebendaan. Penguasaan manusia atas manusia lainnya, bahkan penindasanmanusia atas manusia lainnya, akan terus hadir, baik atas nama agama ataupunatas nama kekuasaan itu sendiri. Kelicikan, saling memanfaatkan, kecemasan,keculasan akan terus berhadiran ketika tujuan-tujuan politik dipisahkan daripenghambaan sepenuhnya manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, politik Islamseharusnya bermakna pembebasan manusia dari belenggu-belenggu mistik dantakhayul, kemudian pembebasan manusia dari tujuan-tujuan kekuasaan yang sekadarduniawi-kebendaan semata. Dengan demikian, tujuan utama politik (dalam Islam)seharusnya ialah pemuliaan manusia di dunia dan akhirat sebagai hamba sekaliguskhalifah Tuhan.
Rujukan:
Comte,Auguste. 1865 (2009). A General View ofPositivism. Cambridge—New York—Melbourne: Cambridge University Press.
Weber,Max, H.H. Gerth, C. Wright Mills (terjemah). 1946. From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford: Oxford UniversityPress.