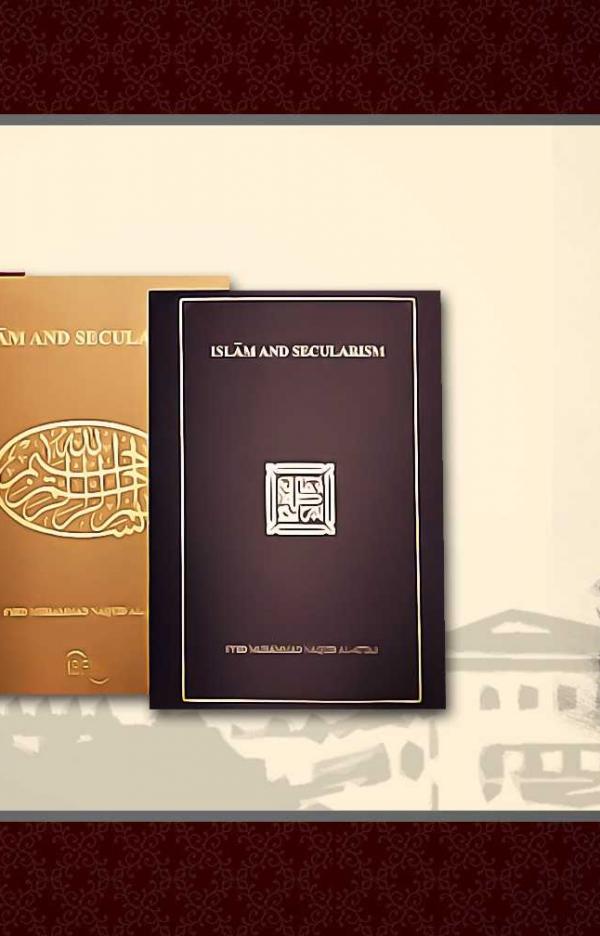Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.
Begitulah Raja Ali Haji menyatakan dalam Gurindam XII. Sementara orang Sunda punya peribahasa yang bunyinya “Jelema mah hade goreng ku basa!”. Kira-kira artinya seperti ini: “manusia itu, baik atau buruknya tersebab oleh bahasa”. Kedua pitutur tersebut menunjukkan betapa penting kemampuan berwicara pada insan dan kemudian pada sebuah bangsa.
Wicara merupakan laku utama insan di mana bahasa menjadi sarana bagi laku tersebut. Wicara lah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menyebut insan (man) sebagai animal rationale, secara ringkas dapat diterjemahkan sebagai makhluk hidup yang berfikir. Sementara dalam tradisi Islām dikenal perkataan al-Insān huwa al-ḥayawān al-nāṭiq, bahwa insan adalah makhluk hidup yang berfikir.
Pokok utama dalam gagasan rationale atau pun al-nāṭiq ialah kemampuan berwicara. Berwicara ialah laku ruhani insan. Suatu daya yang terkandung dalam jiwa. Saat kita mengucap kata-kata, memanglah lidah kita yang melisankan bunyi. Namun maksud, tujuan dan makna dari pelisanan tersebut sebenarnya bukan hasil dari tindakan tubuh. Jika pun bahasa diterjemahkan sebagai tata-susun tanda (system of signs) yang memiliki makna, maka tata-susun tanda tersebut bukanlah suatu peristiwa ketubuhan saja. Bahasa bukanlah suatu tindakan otak (brain) berupa reaksi saraf (neuro) atas rangsangan dari dunia luar tubuh, melainkan suatu tindakan aqliyah yang bersifat ruhani.
Makna, maksud dan tujuan dari suatu pelisanan kata sebenarnya merupakan laku aqal kita, jiwa kita. Begitu pun saat menulis di atas kertas, atau di layar komputer. Kata-kata yang mengalir tergurat bukanlah hasil tindakan ketubuhan melalui tangan. Melainkan jiwa lah, aqal lah, yang mengalirkan makna, maksud dan tujuan bahasa yang kemudian dimanifestasikan dalam aksara yang digoreskan jemari kita.
Pun halnya saat kita mendengarkan seseorang. Bukan saja telinga yang mendengar gelombang suara, namun jiwa yang menangkap makna, tujuan dan maksud dari ucapan. Demikianlah halnya saat kita membaca. Bukan mata saja yang bertindak menangkap maksud di sebalik aksara. Lebih jauh dari itu, aqal kita lah yang bergopoh payah menangkap makna.
Maka berwicara ialah laku antar jiwa. Baik melalui pelisanan atau pun keberaksaraan, wicara sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak. Jiwa yang baik, aqal sehat yang terbimbing ilmu, tentu akan menuturkan bahasa yang indah penuh makna pemupuk keadaban insan. Sebaliknya jiwa penuh amarah, kegelisahan dan kegusaran yang tenggelam dalam kembimbangan akan mengejawantahkan kata-kata kelam yang mengangkut makna-makna gelap.
Seorang pendengar, seorang pembaca, dengan jiwa kukuh yang dibina ilmu, tentu dapat menimbang lisan dan tulisan pihak lain dengan kekukuhan jiwanya itu. Dengan daya aqliah yang tangguh rapi ia akan menimbang tata-susun kebenaran di balik kata-kata. Apa yang indah dan benar akan ia terima, apa yang kelam dan keliru akan ia tapis dan pilah atau bahkan ia tolak dengan seksama.
Menulis dan membaca ialah tindakan antar jiwa. Berucap dan mendengar adalah tindakan ruhani manusia. Bukan sekadar kata, ia adalah perhubungan makna. Insan ialah makhluk yang dapat saling memahami. Wicara hakikatnya merupakan laku utama penunjuk keinsanan seseorang.
Pada taraf ini lah kita dapat memahami apa yang disebut Raja Ali Haji sebagai “bahasa” dalam gurindam di atas. Mutu bahasa seseorang menunjukkan ketinggian ilmunya, kedalaman aqalnya, mutu keinsanannya dan akhirnya laku ruhaninya, keadaan jiwanya. Barangsiapa yang berbahasa dengan baik, itulah penunjuk tertibnya tata-susun berfikir dalam aqal. Barang siapa berbahasa dengan tulus ikhas, itulah penunjuk kemanisan budi yang dikandung diri.
Pun sebaliknya, jiwa yang kelam dapat kita teroka dari rikuh dan lelahnya kata yang ia lisankan. Kata yang dipunggungnya mengangkut beban makna gelap. Kata-kata yang berasal dari keresahan tanpa ujung, kecurigaan tak berkesudahan dan kebimbangan tanpa kepastian. Jiwa yang gelisah terhimpit penuh duka dan luka senantiasa mencari pelegaan sementara. Bahasa sedemikian ialah penunjuk kerontang jiwa gersang yang tak menemukan kepastian.
Pada akhirnya berwicara melalui bahasa ialah hakikat keinsanan kita. Barang siapa yang menjaga bahasanya, mengatur tertib tata-susun pitutur katanya, dia lah orang yang merawat dengan seksama jiwanya, aqalnya. Barang siapa yang meliarkan kata dan tuturnya, dia lah orang yang meranakan jiwanya sendiri.
“Jelema mah hade goreng ku basa!”