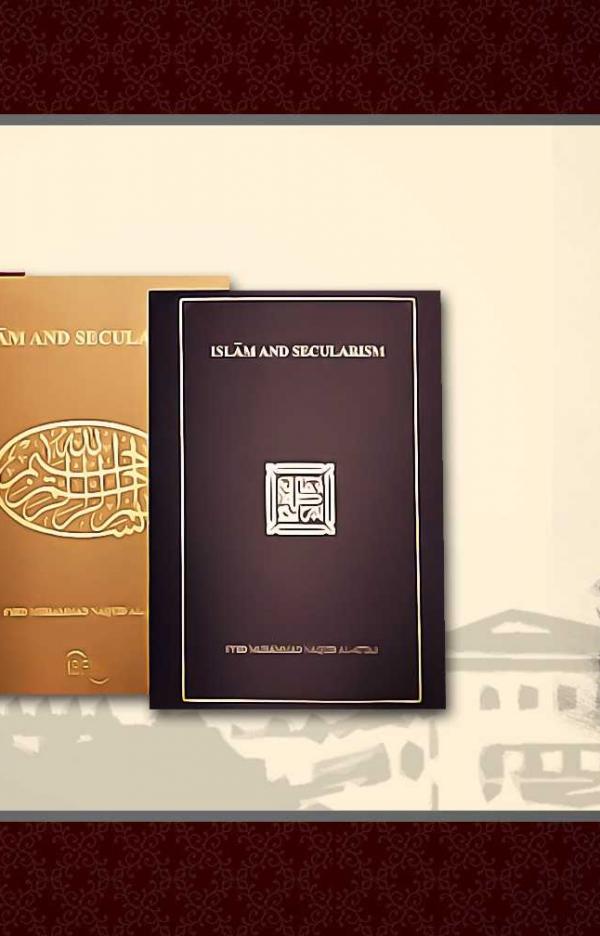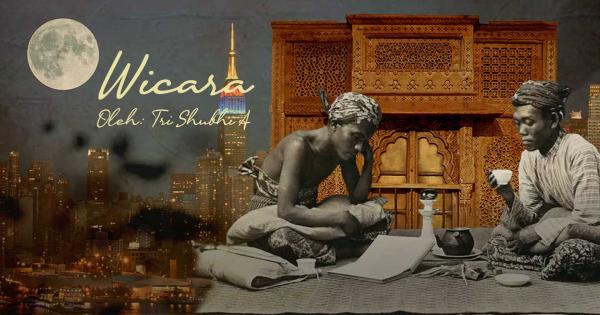Kita hidup di zaman sengkarut maya yang riuh dengan tanda. Di mana sang tanda terhubung amat longgar dengan makna. Jutaan tanda berdesak-desakan di media informasi, menjejali fikiran kita melalui telepon genggam. Padat dan sumpek, memampati saluran-saluran nalar dan kejernihan. Informasi mengendap di jiwa yang tohor, berkerak mengabur-menghablur-menghempas kita ke sekian jarak dari kebenaran.
Hari-hari kita ialah padatan keputusasaan yang ngilu. Kita terombang-ambing dalam urutan rutinitas jemu dan berbagai kerusakan sistem sosial politik yang tak dapat kita atasi. Kita sudah lelah dengan tumpukan tagihan bulanan dan berbagai peristiwa politik yang mengecewakan. Kita tak mampu lagi untuk sekedar mengucapkan “lawan!”. Kita tak mampu untuk sekadar yakin bahwa kita dapat memperjuangkan keadaan yang lebih baik. Kita gugup dan tak percaya diri pada kemampuan kita untuk mengatasi persoalan kehidupan.
Kebudayaan kita ialah kebudayaan limbung yang bising dengan suara pesimis dan nisbi. Di mana manusia dinilai tak lagi mampu mengakrabi makna, akalnya dianggap kalah canggih dibanding bermacam perangkat simbolik teknologi informasi. Deras arus kebenaran dan kepalsuan bersilangan susul-menyusul sesak-menyesaki hari-hari kita, lebih cepat dari kemampuan laju fikiran manusia. Dunia kita telah tak percaya pada pencapaian insan akan makna. Zaman ini ialah zaman porak poranda yang jorok dengan pesimisme terhadap segala yang menjanjikan kepastian dan keyakinan mutlak. Dunia kita ialah dunia tunamakna yang beku, tajam, sepi dan hampa.
Kita terjebak, tak dapat melarikan diri dari longsoran realitas rumit yang menimpa nasib kita. Kita diajari untuk mencintai makna sejak dahulu di masa kelahiran. Diupacarai dan disambut dengan berbagai tanda yang mengangkut makna-makna setaraf do’a. Namun pada kenyataannya kini, kita hidup di lorong gelap tanpa awal dan ujung. Kita tak punya pilihan selain terus menyusuri lorong kehidupan, tak dapat kembali kepada masa lalu yang menyenangkan, tak pula dapat memastikan masa depan yang membahagiakan.
Kita adalah manusia yang terjebak dalam timbunan tanda, putus asa, limbung dan tak dapat bernafas dengan bahagia. Kita terlempar pada suatu dunia tunamakna.
Benarkah demikian?
Kita memang hidup dalam kebudayaan maya yang mengkilat terang disorot cahaya kemewah-megahan teknologi. Namun kita masih manusia yang sama, manusia yang dapat menyiram bunga di pagi hari sambil menikmati secangkir kopi dan mengobrol ringan bersama keluarga. Kita masih manusia yang mengobrol, berbicara, mengudar rasa satu sama lain, sama seperti dahulu kala, saat dunia belum mengenal listrik dan internet. Kita masih makhluk berwicara yang dapat takut atau pun berani terhadap sesuatu di luar diri kita.
Di zaman ini, kita tetap dapat bangun pagi, berdo’a dengan khusyu untuk kemudian menanam sawi. Kita masih berdaulat atas diri kita dan tetap makhluk wicara yang diberkahi akal. Oleh karenanya, setunamakna apa pun zaman, kita tetap dapat menyigi keinsanan kita, menjaga daya beraksara dan menyanggupkan diri untuk mengarungi zaman.
Kita perlu membangun keakraban, memberi pengertian, mengerti manusia lain dan dimengerti manusia lain. Kita akan terus menjaga asa keinsanan, menata ketulusan melalui kata, sebab makhluk yang berwicara ialah dia yang mampu mencinta dan dicinta. Insan yang mampu menaklukan benci, dengki dan iri.
Perhubungan antara manusia yang sesungguhnya, ditempuh jiwa wicara, arti paling asas bagi keinsanan. Dan menulis ialah di antara sarana memperhubungkan jiwa kita secara aqliah dengan jiwa lain. Ia bukan suatu proses pelegaan dari kecemasan. Kata-kata yang mengalir dari alam pandang kita, bukan kata yang berasal dari tetes-tetes katarsis dan tragedi.
Jiwa wicara ialah jiwa yang bersedia menelusur segala luka dan rahasia, bersabar atas segala cerita. Ia menyampaikan dan menerima makna, menebar dan mendekap cinta. Sang wicara ialah sarana bagi jiwa untuk berkelana, menjelajahi kata dengan kebersediaan menerima pedih yang tak ada batasnya hingga sampai kita kepada makna. Inilah suatu rindu asali insan untuk bertemu dengan yang namanya kebenaran.
Kita masih perlu merajang kata, menyajikan maksud dengan sepenuh cinta kepada jiwa lain melalui aksara. Menulis masih saja seperti dulu, ialah cara kita merunduk rendah pada Sang Pencipta. Sebentuk kesyukuran atas karunia aqal dan jiwa yang segar. Ia seperti sebuah kelahiran yang berasal dari cinta. Mengajar kita untuk jujur pada diri sendiri.
Mari bergabung bersama kami. Menyigi diri, meraut daya beraksara. Membangun kemampuan aqliah, mengolah dan menghayati kata.
Marilah kita terus menulis. Merajang kata, meski dunia semakin tunamakna.
***