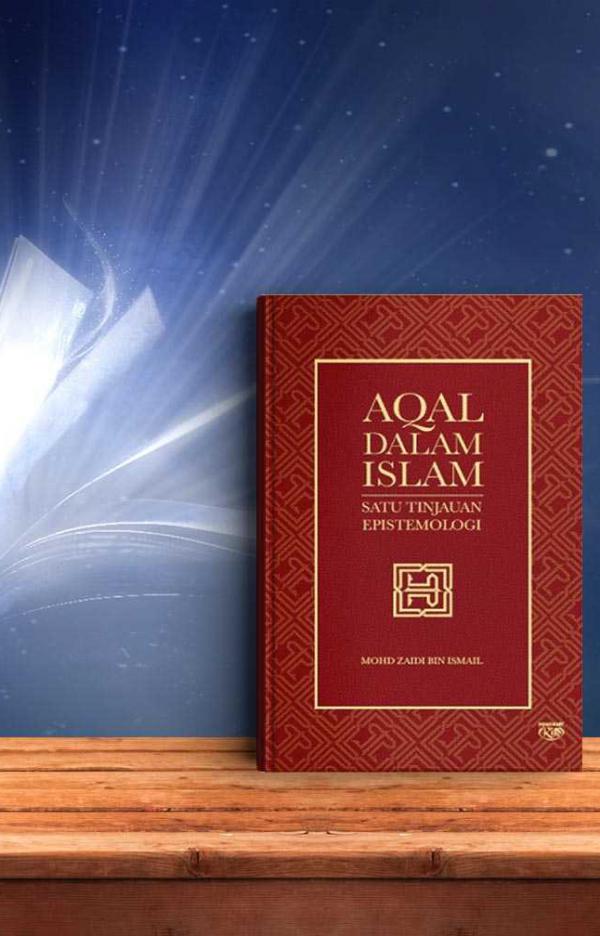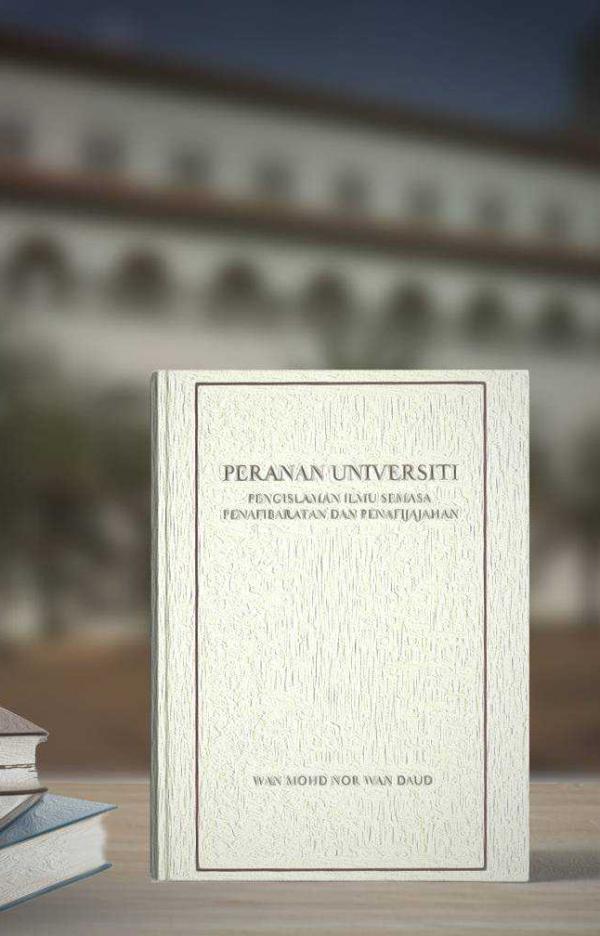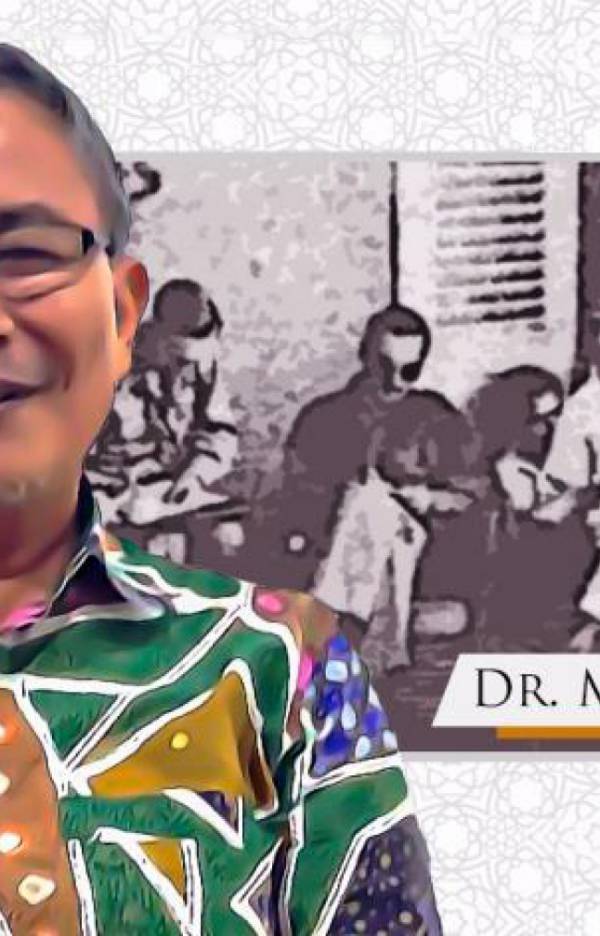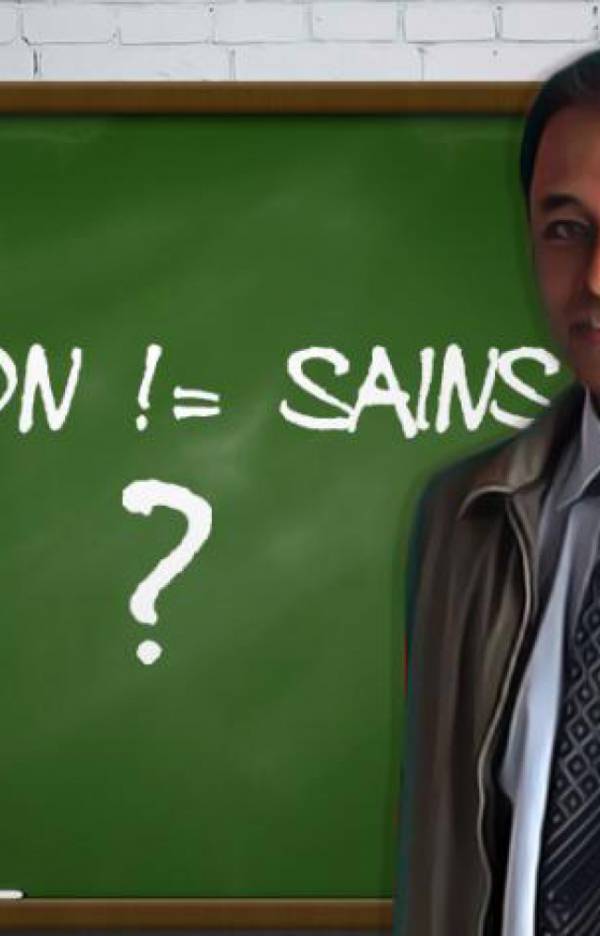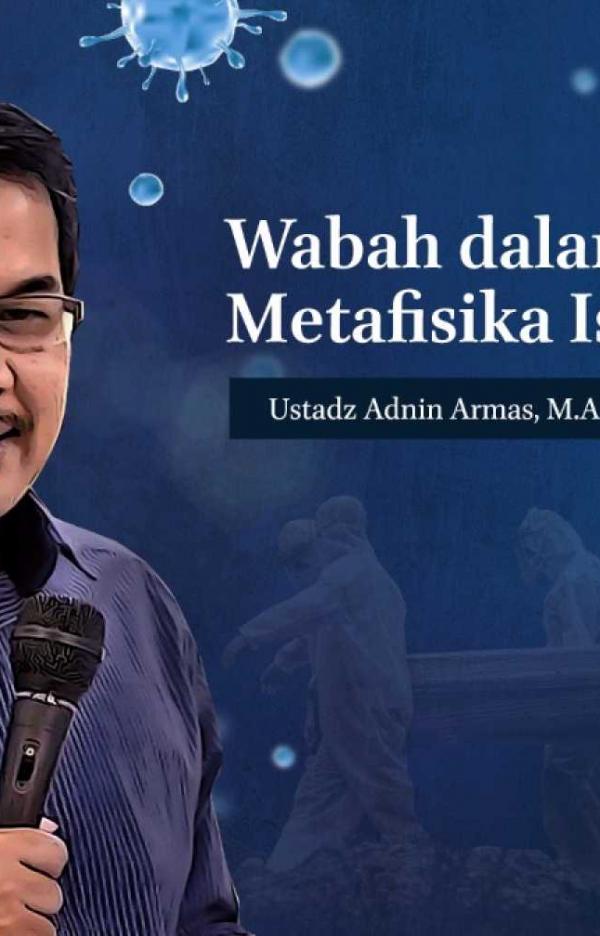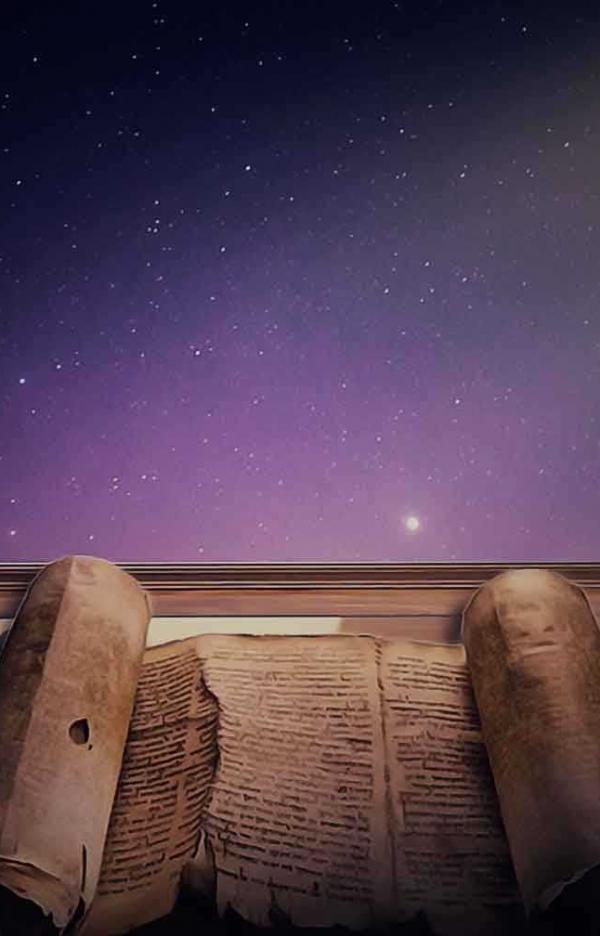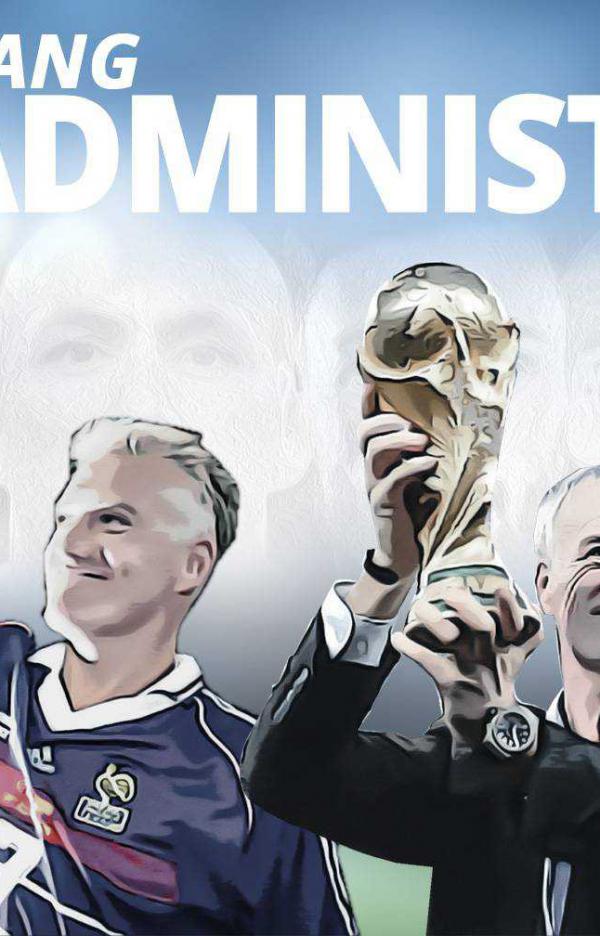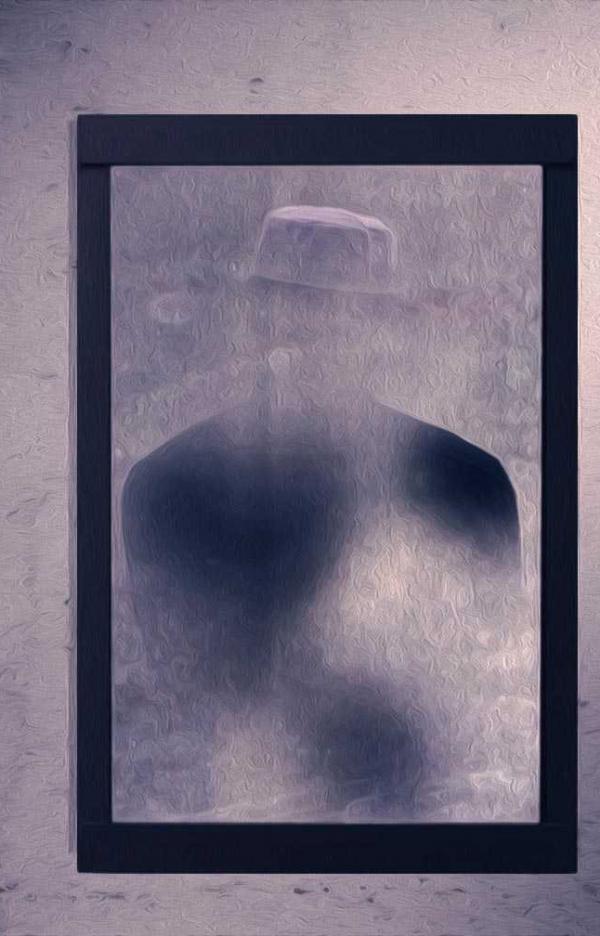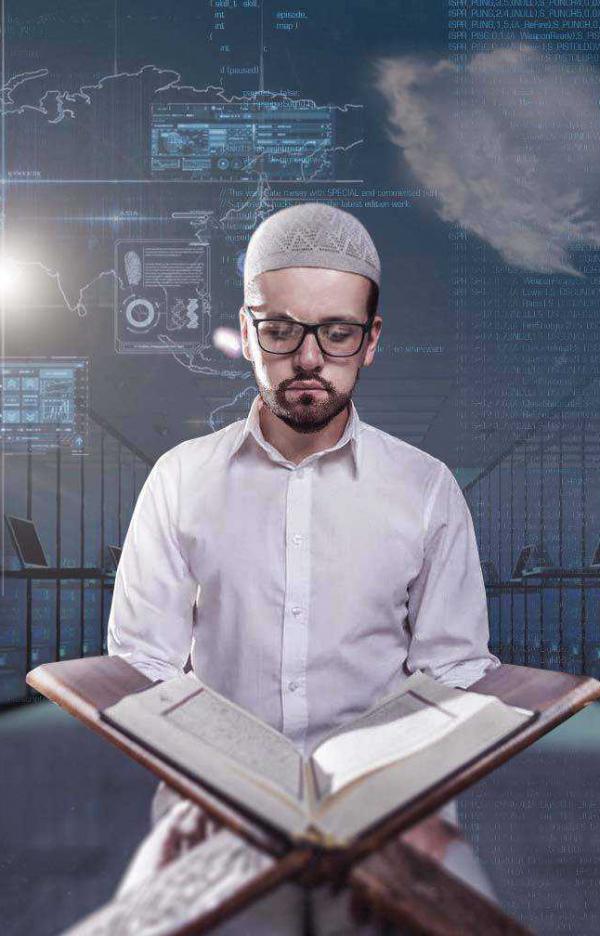Ikhtiar Berpikir Runtut, Bicara Patut, dan Saling Tuntut
Pernah suatu masa, umat Islam berpolitik dengan elegan dan bermartabat. Mereka turut berdebat tentang dasar negara, mulai dari penyusunan Undang-Undang Dasar dengan Piagam Jakarta sebagai pokok pangkalnya hingga perdebatan di konstituante yang sayangnya tak tuntas dan terhenti dengan terbitnya dekrit presiden 1959. Tentunya ada kekecewaan. Saat itu, penerbit dekrit memberikan hiburan dengan pernyataan, “Piagam Jakarta menjiwai UUD NRI 1945.â€
Reformasi memberikan angin segar bagi umat, khususnya terkait positivisasi syari’at. Hampir semua partai islam dan berbasis Islam menjadikan syari’at islam sebagai jargon perayu pemilih. Roda waktu berputar, partai pengusung positivisasi syari’at satu per satu undur diri dari gelanggang hingga wacana itu makin lamat-lamat. Kalaupun ada yang setia dengan jargon tersebut, terseok-seok di dasar klasemen, tak melampaui parliamentary threshold. Partai islam yang lain tak kunjung selesai dengan dirinya, baku hantam dengan sudara sendiri serta saling berebut legalitas dan representasi. Jangankan memikirkan keumatan, melerai saudara serumah pun tak kunjung berhasil.
Trend negatif ini sejalan dengan hilangnya nama-nama besar potensial umat, sebagian tersandung hukum, ada yang tidak istiqomah, dan berbagai sabab lain. Dalam dua pemilu terakhir, praktis, umat islam hanya menjadi penggembira, menjadi follower, bukan lagi trend setter seperti masa kemerdekaan, tahun 50-an, dan masa peralihan reformasi 98.
Kini, Kita terpaksa memberikan label Islam pada tokoh yang bukan secara organik lahir dari rahim politik umat islam. Mereka memang muslim, tapi tak benar-benar islami dan paham benar hajat hidup umat Islam.
Partisipasi politik umat di parlemen pun kian menyusut. Akhirnya, jalan yang dipakai adalah jalur non-negara. Umat berkerumun di jalan-jalan, di lapangan terbuka, dan meramaikan media sosial. Ada trend menggembirakan. Umat mulai menanggalkan sekat-sekat ideologis mazhab, ormas, dan partai. Mereka menyatu dalam satu rasa dan prinsip: keimanan. Pertanyaannya: efektifkah? Mampukah kita membungkam pengkritik yang bilang bahwa kerumunan itu hanya buih-buih di lautan?
Jika mau jujur menilik ke dalam raga umat, melakukan autokritik, kita telah keliru merasa dan keliru berpikir. Kita keliru dalam mengekspresikan gagasan searah, lebih jauh lagi menjadi kekeliruan dalam komunikasi dua arah.
Dewasa ini, kita disuguhi berbagai perbincangan, jual beli gagasan, dan perdebatan di ruang publik yang jauh dari kata berkualitas, baik dari segi konten maupun kemasan. Problem tersebut bertitik pangkal pada ketiadaan atau lemah dalam berpikir runtut dan berbicara patut serta saling tuntut. Suatu kondisi umat belum mampu memenuhi kriteria logis, retoris, dan dialektis.
Berbincang-bincang soal berpikir runtut, semenjak 2014, kita seperti hidup dalam keterancaman. Orang mengipasi kecemasan akut yang kita derita. Kita menjadi pasar dan alat. Benci dan fanatisme dikedepankan, rumus berpikir dikesampingkan. Ada ketidaknyamanan dan sumbatan kebudayaan, praduga dan syak wasangka. Kita merasa terancam oleh sesuatu yang tidak benar-benar terbukti. Marah dan senang dahulu, berpikir kemudian. Semuanya mencapai kulminasi, keterburuan mengambil keputusan dan kesimpulan serta kecepatan melupakan persoalan. Titik pangkalnya adalah ketidakmampuan kaum muslim mempraktikkan yang mereka pelajari. Sebagai contoh: di sebuah pesantren yang mengajarkan ilmu maná¹iq, di Kobong, kamar tempat siswa, kita temui pemandangan tak lazim. Beras, kitab, dan ikan asin, bisa berkumpul dalam satu wadah yang sama. Suatu yang musykil diterima, mengingat mereka mempelajari taqsim, klasifikasi.
Kita juga tak mampu bicara patut, terjadi silang pendapat tak berkesudahan sesudah pilpres (pemilihan presiden) 2014 dan pilgub 2017. Kita terbelah pada dua kubu secara diametral dan ekstrem, pembela utama dan pencaci setia.
Selanjutnya, kita bermasalah dalam saling tuntut. Saling merendahkan, mengejek, dan menyindir menjadi keseharian. Kebohongan dan “berita hitam†menjadi kebiasaan.
Ketiganya dapat, secara perlahan, difahami dengan pendekatan ilmu maná¹iq, balÄghah, dan munÄẓarah atau jadal. Kalau istilah orang Barat: logika, retorika, dan dialektika.
I. Berpikir Runtut (Logis)
Aristoteles diakui sebagai peletak batu pertama ilmu Maná¹iq (Logika). Porpyrius kemudian menyusun dalil-dalil logika Aristoteles secara sistematis (268--270 CE). Susunan Porpyrus ini disalin dan dilengkapi oleh AtsÄ«ruddÄ«n Al AbharÄ« (1265 CE) dalam bahasa Arab dengan tajuk ’IsÄghujÄ«. Lalu, muncul ar-RisÄlat as-Syamsiyyah oleh NajmuddÄ«n Al-KÄá¹ibÄ« (w 675/1276 CE). Selanjutnya, al-Akhá¸arÄ« (w 1546 CE) melakukan penyederhanan dari susunan yang tersebut dalam karya utamanya, Sulam al-Munauraq. Peradaban Barat wajib berterima kasih pada Boethius yang menterjemahkan Isagoge ke dalam bahasa Latin. Proses bernalar warisan Aristoteles yang disempurnakan oleh peradaban Islam sampai pula ke peradaban Barat sehingga mengantarnya menuju zaman modern.
Banyak sekali kajian ilmu maná¹iq. Secara umum, ilmu tersebut mencakup:
-         ta‘rīf dan dalīl (definisi dan argumen)
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â idrÄk (proses penalaran)
-         ma‘qÅ«lÄt (kategori)
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â kuliyat al-khamsah (spesies, genus, differentia, common accidents, dan proper accidents)
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â qiyÄs (silogisme)
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â khaá¹a burhÄn (sesat pikir)
Ta’rif dan Dalil
Ta’rif (definisi) yang baik harus mampu men-jam‘u yang semestinya di-jam‘u (mengikat yang semestinya diikat) dan me-man‘u yang semestinya di-man‘u (mencegah masuknya anasir yang semestinya dicegah dan tidak masuk dalam definisi). Contoh definisi yang tidak mampu men-jam‘u (tidak mampu mengikat yang semestinya diikat):
Manusia adalah makhluk primata dan mamalia yang berkulit putih. Definisi ini tidak mampu mengikat orang Negro, Aborigin, Asmat, dan sebagainya dalam label manusia.
Contoh definisi yang tidak mampu mencegah masuknya unsur asing :
Manusia adalah makhluk hidup yang termasuk primata. Karena definisi ini terlalu sederhana, orang utan pun masuk dalam golongan manusia karena dalam definisi ini tidak ditambahkan persyaratan lain yang mampu mencegah masuknya orang utan, siamang, atau gorilla dalam lingkup manusia.
Beberapa komponen ta‘rīf :
- Taá¹£awwur: idrÄku mufrodin (mengetahui dan memahami suatu fenomena tunggal--kata). Untuk pendekatan pemahaman, tashawwur dapat diartikan gambaran benak.
- Taá¹£dÄ«q: idrÄk al-qaá¸iyyah (mengetahui dan memahami kesatuan kalimat--pernyataan).
- Qaá¸iyyah (preposisi) adalah kalimat yang berisi pernyataan--berita.
Contoh qodiyah: Zaid Berdiri.
Qaá¸iyyah terdiri atas tiga unsur:
- Mauá¸u‘ (mubtadÄ’/‘subjek'): Zaid, dalam balÄghah disebut musnad ilaih (sesuatu yang disandari oleh sifat, atribut atau predikat).
- MaḥmÅ«l (khabar/‘predikat') dalam balÄghah disebut musnad. Dalam contoh di atas: berdiri.
- ThubÅ«tul mahmÅ«l lil mauá¸u‘ atau ThubÅ«tul qiyÄm lil Zaid, adanya atribut atau sifat dan keadaan berdiri yang disematkan pada diri Zaid, disebut nisbat (hubungan mauá¸u‘ dengan maḥmÅ«l), dalam sumber lain dikenal istilah rÄbiá¹ah.
Memahami mauá¸u‘ dan maḥmÅ«l secara parsial (tidak paripurna), disebut taá¹£awwur, hanya faham makna Zaid saja atau berdiri saja. Dengan adanya taá¹£awwur, timbullah ta‘rÄ«f (definisi).
Memahami mauá¸u‘ (Zaid) dan maḥmÅ«l (berdiri) sebagai suatu kesatuan yang utuh dan nisbat (hubungan) antara keduanya (berdirinya Zaid), disebut taá¹£dÄ«q. Setelah selesai proses taá¹£dÄ«q, maka dihasilkanlah dalÄ«l (argumentasi).
Contoh redaksi bahasa Arab: Muḥammadun RasÅ«lullÄhi.
HÄdhihi qaá¸iyyatun mÅ«jabatun, fa muḥammadun á¹¢alla’llÄhu ‘alaihi wa sallam mauá¸u‘ (ini adalah contoh qadiyah mujabah, Muhammadun SAW adalah mauá¸u‘ ‘subjek’) wa RasÅ«lullÄhi maḥmÅ«l (dan RasÅ«lullÄhi adalah maḥmÅ«l ‘predikat’). FaidrÄku ma‘na Muḥammadin huwal mauá¸u‘ (ketika Anda faham makna kata Muhammad, Anda telah memahami subjek) , wa idrÄku ma‘na RasÅ«lillÄhi huwal maḥmÅ«l (ketika Anda faham lafaz Rasulullahi, Anda telah memahami predikat). Wa idrÄkuka al yaqÄ«niy bi thubÅ«tirrisÄlati lisayyidinÄ Muhammadin á¹¢alla’llÄhu ‘alaihi wa sallam taá¹£dÄ«q (saat Anda memahami dan yakin atas adanya risalah kenabian dan kerasulan pada diri Muhammad á¹¢alla’llÄhu ‘alaihi wa sallam, itulah yang disebut dengan taá¹£dÄ«q ‘membenarkan dengan sepenuh hati’).
II. Bicara Patut (Retoris)
Setelah berpikir secara sistematis (runtut), manusia mesti mengartikulasikan buah pikirnya dengan lisan lalu didokumentasi dengan tulisan. Hal ini menyangkut kepatutan pembicaraan sesuai konteks waktu, tempat, dan lawan bicara (muqá¹ÄḠal-hal, muqá¹ÄḠal-maqÄm, atau muá¹Äbaqah) sesuai dengan prinsip: likulli maqÄmin, maqÄlun (bagi setiap tempat, terdapat pembicaraan yang tepat).
Ujaran yang baik disebut faá¹£Ähah (benar tata bahasanya). Di atasnya, terdapat predikat balÄ«gh (sesuai dengan kaidah balÄghah atau retorika).
Khatib QazwÄ«nÄ« (w 1338) dalam TalkhÄ«sul MiftÄh mengklasifikasi BalÄghah menjadi tiga:
- Ma‘ÄnÄ«: secara mendasar membahas hubungan musnad ilaih (subjek) dengan musnad (predikat) dari sudut pandang makna. Adapun segi lafaz merupakan tugas gramatika (nahwu). Singkatnya, ma‘ÄnÄ« adalah ruh gramatika. Dalam ma‘ÄnÄ«, didedah pula khabar dan insya’ (ujaran atau berita dan perintah), Ä«jÄz dan itnÄb (ringkas dan panjang ujaran), dan lain sebagainya.
- BayÄn, mempelajari berbagai gaya bahasa; haqÄ«qat dan majaz (denotatif dan konotatif), isti’Ärah (metafora), dll..
- Badi': ilmun bihi wujuhu tahsinil kalam, ilmu tentang seni memperindah pembicaran. Di dalamnya, terangkum keelokan lafaz dan keelokan makna, bahasan tindak plagiat, teknik mengutip, dan sebagainya.
Masyarakat Nusantara sedari dulu telah mempelajari ilmu-ilmu ini, jauh sebelum politik etis didengungkan oleh van Deventer pada 1901. Buku pegangan bagi murid pemula dalam balÄghah adalah Jauhar Maknun (Al Akhdori); tingkat berikutnya: Uqudul Juman (Assuyuthi, w 1505 CE)
III. Saling tuntut (dialektis)
Saling tuntut merupakan tahap ketiga setelah berpikir runtut dan bicara patut. Yang saya maksud adalah saling menuntut dalil dari lawan bicara. Saling tuntut sudah pada level dialog, berbeda halnya dangan dua yang pertama, masih monolog. Pada tahap ini, kedua pihak saling mendakwa, ber-mu’arodloh, saling gugat, dan ber-mujadalah. Ilmunya disebut ilmu jadal atau munÄẓarah. Pemeran dalam dialog ini terdiri dari dua: mustadil dan mu’taridl (pro dan kontra). Pada level dasar, diatur etika mufti dan mustafti, pemberi fatwa dan pemohon fatwa. Khazanah modern mengistilahkan dialektika, kata bersifat dialektis. Khazanah keilmuan klasik bidang jadal di Nusantara banyak menggunakan sumber Turki Utsmani, di antaranya: QubrÄ ZÄdah (Taá¹£kubra ZÄda) dan HamÄmÄ« ZÄdah. Di antara nama kitabnya: al-Waladiyyah.
Pada peringatan 100 Tahun almarhum Prof. H.M. Rasjidi, 20 Mei 2015, di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, almarhum merupakan guru logika dan filsafat bagi dirinya dan rekan sebayanya, yakni Prof. Yusril Ihza Mahendra. Putra Palembang dan Belitong ini, setiap pekan, sorogan pada sang profesor lulusan Sorbonne dan pengajar di McGill. Seiring waktu berlalu, mereka berdua mewarnai jagat keilmuan negeri ini dengan ujaran dan tulisan yang selalu renyah dan layak konsumsi. Skill tersebut tentu tidak mewujud dengan sendirinya, tetapi tumbuh melalui proses panjang, tak terkecuali melalui interaksi dengan Prof. H.M. Rasjidi dalam hal dasar-dasar logika.
Ruang publik akan kering kerontang, miskin inovasi, dan jauh dari keteraturan tanpa logika, retorika, dan dialektika. Masih ada waktu menata diri. Masih ada kesempatan menyongsong 2019. kita periksa kembali yang telah kita bagikan di media sosial, Facebook, Twitter, Whatsapp, dsb.. Untuk menciptakan perbincangan dan jual beli gagasan yang tertib dan bermutu diperlukan laws of the game, rumus-rumus baku yang terangkum dalam tiga kata kunci: berpikir runtut (logis), bicara patut (retoris), dan saling tuntut (dialektis).
Jakarta, 4 Dzulqa’dah 1438 H (27 Juli 2017)