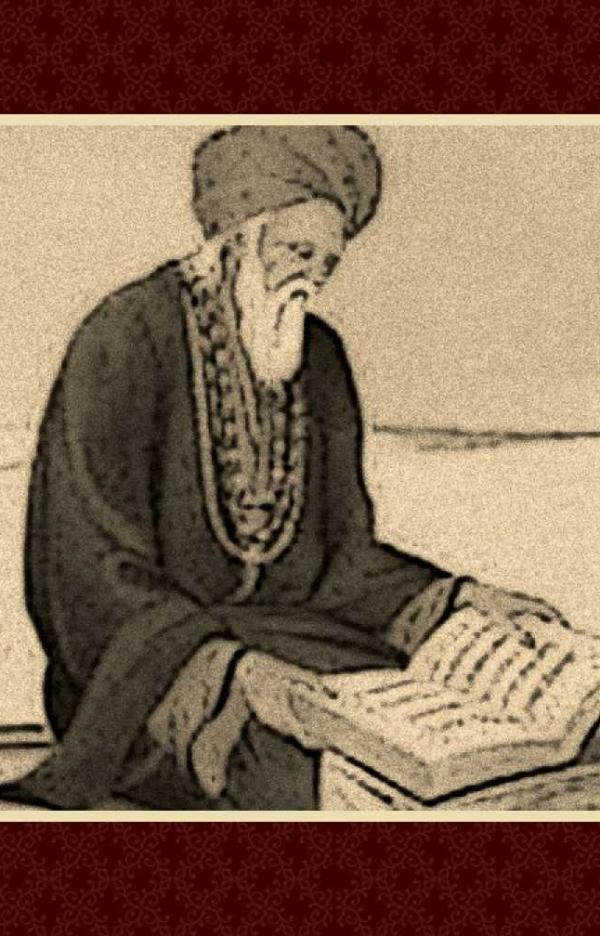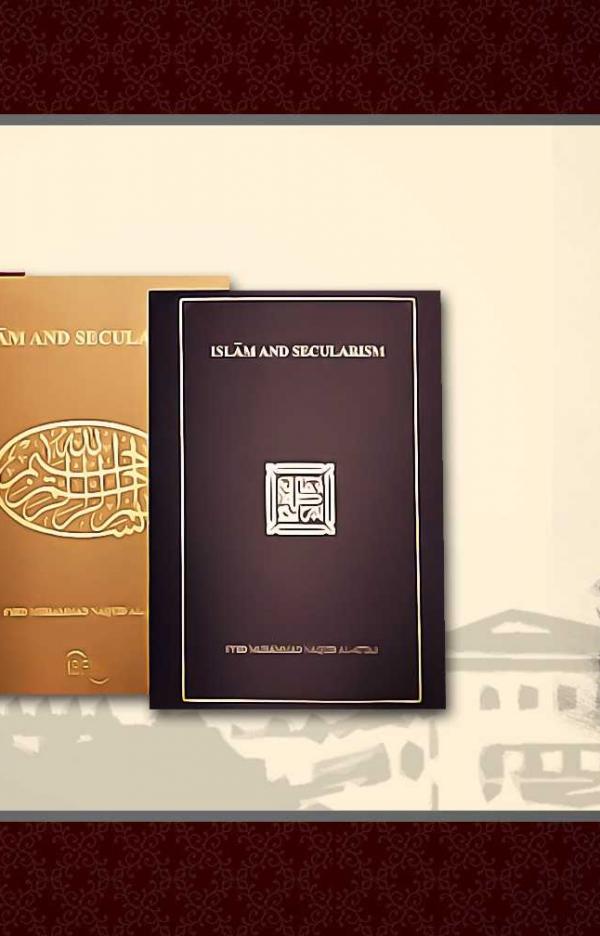Belasan anak kecil bermain sepak bola di lahan lapang samping kiri Masjid Luar Batang. Para remaja dan orang tua sibuk mempersiapkan panggung acara Isra Mi’raj di halaman depan masjid. Pedagang menjajakan makanan di sekeliling tembok dan halaman depan masjid. Seorang petugas keamanan lagi menggunakan jasa pencucian motor di depan tembok masjid. Sebuah tulisan tertera di satu sudut tembok masjid, “KANSASS (KAMI ANAK NAKAL SUATU SAAT AKAN SADAR).â€
Rumah-rumah permanen berdiri di selingkar Masjid Luar Batang. Ada rumah berlantai dua, ada juga yang cuma berlantai satu. Dempet satu sama lain. Tak ada gang pemisah. Tak ada halaman. Tak ada tanah merah dan hanya sedikit pohon. Panas. Spanduk-spanduk yang marah terhadap gubernur yang berencana menggusur kampung sekitar masjid menambah panas suasana sekitar.
Depan rumah langsung menghadap masjid dan jalan-jalan selebar empat meter. Cukup untuk lewat dua mobil. Tapi pengemudi mobil bakal kesulitan jika ada motor parkir di tepi jalan. Salah satu mobil harus mengalah untuk kasih kesempatan mobil lain berjalan.
Dalam kepadatan demikian, warga bercengkerama di tepi jalan. Mereka menatap masjid dan apartemen jangkung di seberangnya. Wajah dan pakaian mereka beraneka rupa. Dari tampang preman, kasar, gelap, teduh, tampan, cantik, kumal, sampai cerah. Mulai pakaian oblong, singlet, daster, hingga baju koko putih. Semua ada.
Sabtu sore, 8 Mei 2016, kami dari Komunitas Nuun bertandang ke Masjid Luar Batang. Ini kali pertama kami ke sini. Pertandangan ini merupakan awal pelaksanaan rencana kami menyambangi masjid-masjid bersejarah di Jakarta. Kami ingin tahu peran masjid dalam perkembangan masyarakat Betawi dan Jakarta.
Kami beroleh informasi dari Bang Mathar, tokoh dan budayawan Betawi asal Tenabang, bahwa para ulama dahulu telah menjadikan masjid sebagai titik awal membangun masyarakat berperadaban. Mereka membangun masjid untuk pertukaran informasi dan kabar, pusat ilmu pengetahuan, dan pendidikan. “Para ulama selalu membangun masjid lebih dahulu daripada bangunan lainnya,†kata Bang Mathar.
Masjid Luar Batang tegak sejak abad ke-18. Pendirinya bernama Habib Husein bin Abubakar bin Abdullah Alaydrus. Beliau seorang ulama dari Timur Tengah, datang ke Batavia, lalu memperoleh tempat di benak orang-orang tempatan. Saya tak banyak paham perihal sosok Habib Husein. Hanya pernah dengar nama tersohornya.
Arief, seorang kawan di Nuun, bilang kisah Habib Husein sudah ada bukunya. Kami mencari buku tersebut di toko suvenir Masjid. Arief bertanya kepada penjaga toko, seorang lelaki Betawi keturunan Arab. Penjaga toko menunjukkan letak bukunya. Arief mengikuti telunjuk penjaga buku. Kami melihatnya. Buku saku kecil seukuran buku Yassinan.
Arief menatap saya. Wajahnya mengekspresikan keheranan. “Cuma satu, ya, Bib, bukunya?†Habib mengatakan, “Iya, cuma ini. Emang ini.â€
Arief membeli buku itu seharga 5.000 rupiah. Saya mengambil buku itu dari tangan Arief dan membacanya selintas. Gaya tulisannya kurang menarik. Data dan sumber pendukungnya minim. Buku itu lebih banyak bercerita karomah-karomah (keistimewaan di luar nalar) Habib Husein. Tidak salah, tapi sangat kurang untuk menghargai usaha seorang ulama besar macam Habib Husein.
Seorang Habib Husein yang penuh ilmu, mempunyai rihlah (perjalanan) ruhaniah panjang, dan bertemu dengan banyak jenis manusia pastilah mengandung hikmah seluas bumi bagi berbagai generasi. Ia tak cukup terangkum dalam buku saku kecil.
Kami pamit keluar pada penjaga toko. Saat berbalik, saya melihat sebuah sarung hitam di etalase toko. Saya menanyakan harganya ke penjaga toko.
“65 ribu rupiah aja,†katanya.
Saya sudah lama butuh sarung hitam polos semacam ini. Dan baru sekarang berkesempatan menjumpainya secara langsung. Saya bawa sarung ini. Arief bertanya, “Buat apa, Ru? Saya membalas pendek, “Pokoknya ada, deh.â€
Menjelang maghrib, kami beranjak dari Luar Batang. Kami mampir di Muara Angke untuk menengok kampung nelayan sebentar, kemudian pulang.
Beberapa hari kemudian, saya memakai sarung hitam itu tuk kali pertama. Sekadar tuk menunaikan salat Isya yang sangat telat dan untung ingat. Tapi lama-lama enak juga pakai sarung hitam ini. Ke warung pakai sarung hitam, ketemu tetangga pakai sarung hitam, dan ziarah ke makam juga pakai ini. Bahkan menulis catatan ini sekadarnya pun masih bersarung hitam polos itu. Mungkin ada semangat orang-orang dari Luar Batang di sarung ini yang menyalakan api hidup.
Tiap kali melihat sarung ini, saya melihat Luar Batang. Melihat kepadatan, kekumuhan, dan buku saku kecil kisah ulama besar, dan penghormatan orang-orang terhadap Masjid di Luar Batang. Pemerintah, dalam tataran tertentu, memang benar, bahwa memang ada masalah di Luar Batang. Perlu ada penataan. Tapi penataan itu hendaknya bukan demi pengusaha atau konglomerat. Kita, umat Islam, berupaya menata diri dan kehidupan kita demi wujudnya kembali peradaban masjid sesuai anjuran para ulama dahulu.
Dan melihat keguyuban serta kesatuan warga sekitar mendirikan panggung Isra Mi’raj, memperhatikan keanekaragaman tampilan mereka, saya sangat yakin dan tahu penggusuran bukan satu-satunya jalan untuk penataan. Jalan lain itu selalu ada. Kita bisa berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Kita bisa menyelidiki bagaimana Habib Husein hidup agar mampu mengolah warisan pemikirannya tentang masyarakat dan masjid pada masa lalu untuk masa kini.
Mudah-mudahan, pembacaan itu bisa membuat kita menghargai sebuah buku lebih daripada sarung hitam polos. Tapi ini bukan berarti tangan-tangan terampil pembuat sarung itu lantas kita acuhkan dan rendahkan. Bukan. Ini adalah persoalan tentang bagaimana kita menempatkan sesuatu sesuai kadarnya.