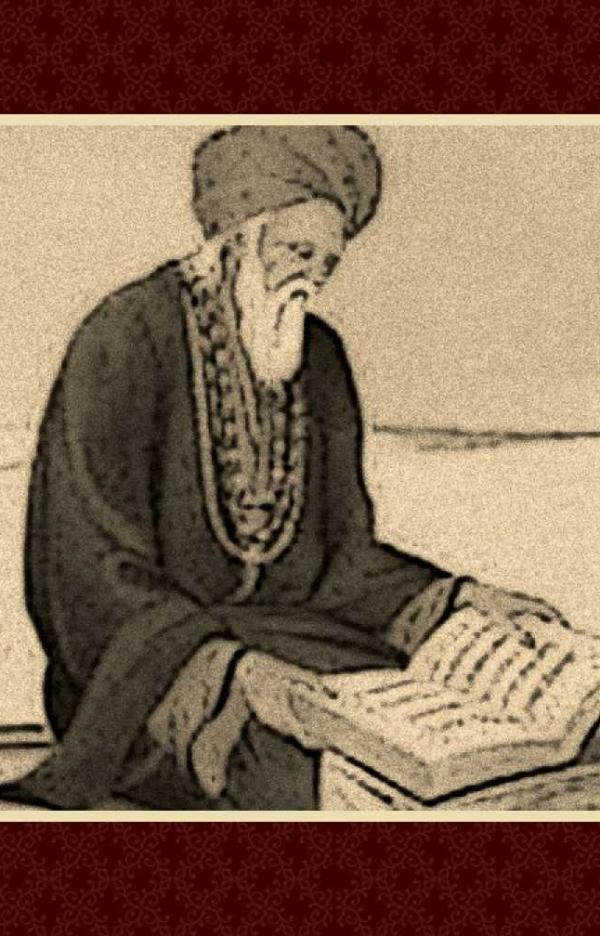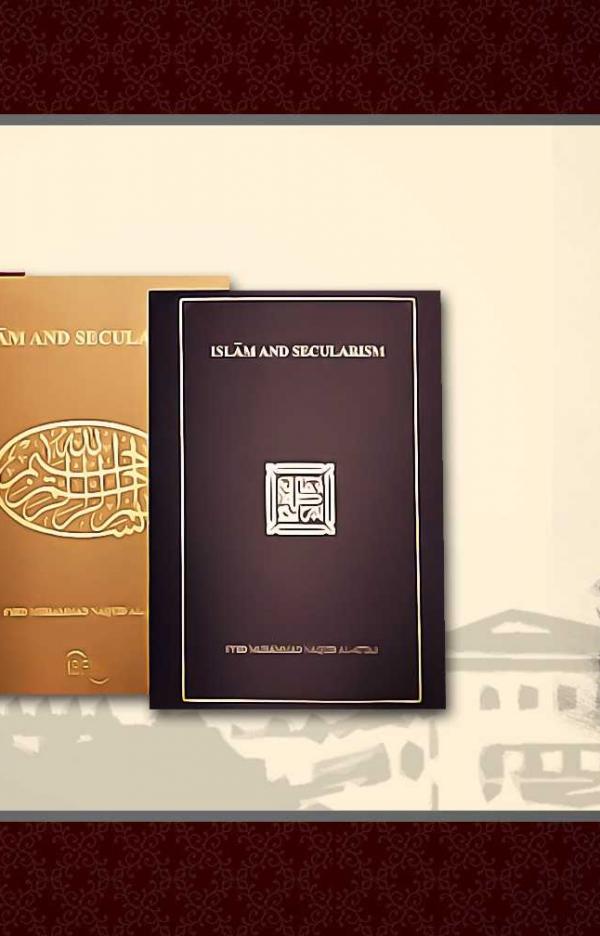Hari ini muslimah dapat merayakan pakaian dengan beragam cara. Warna-warna berbagai dan cara memakai bermacam tampil dalam keseharian berjilbab muslimah kita. Lebih jauh lagi, jilbab telah masuk ke arena peragaan busana, butik-butik ternama, dunia industri, bahkan pergaulan kelas atas. Jilbab tak lagi sekadar pertanda ketaatan dan iman, melainkan juga perlambang gengsi dan ciri pergaulan urban. Berjilbab tak kalah mentereng dari memakai rok mini.
Tentu saja perayaan jilbab semacam itu tak ada salahnya. Namun ada baiknya kita menengok ke masa-masa yang lalu. Pada suatu ketika di negeri ini, jilbab pernah dianggap lambang keterbelakangan, kampungan, anti-kemajuan, dan ketakmampuan mengikuti arus perkembangan zaman. Berjilbab di sekolah atau kampus negeri mendapat tantangan. Kaum muslimah yang berjilbab dianggap ekstrem, tak berkemajuan, dan tak taat aturan. Berjilbab memerlukan perjuangan. Bukan sekadar gaya-gayaan.
Catatan perih sekaligus goresan perjuangan ini terekam dalam sebuah buku berjudul Masjid Arief Rahman Hakim Universitas Indonesia: Masjid Kampus untuk Ummat dan Bangsa. Ada baiknya kita membacai beragam peristiwa perihal jilbab tersebut. Sebab pada akhirnya, berpakaian bagi muslim bukan sekadar gengsi dan gegayaan. Bukan sekadar industri dan perayaan kemodisan. Lebih jauh dari itu, pakaian ialah bagian dari ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya.
Nuun.id menyadur tulisan tersebut dan melakukan penyuntingan seperlunya.
***
Pada dasarnya bangsa Indonesia ialah bangsa yang beragama. Kesadaran beragama pada masyarakat kita cukup tinggi, begitu pula di kehidupan akademik kita. Hal yang sama dialami para mahasiswa aktifis masjid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia (ARH-UI). Kesadaran untuk menjalankan perintah agama dengan sempurna selalu bersemi pada diri aktifis-aktifis itu. Salah satu tanda kesadaran itu ialah perubahan pada tata pakaian kaum muslimah. Kesadaran untuk berjilbab dengan lebih seksama mulai hadir dalam diri pada muslimah, termasuk para mahasiswi di UI. Generasi jilbab di kampus muncul pada awal tahun 80-an dan kemudian menjadi suatu hal yang tidak 'aneh' lagi pada era 90-an. Jilbab menjadi simbol identitas muslimah menandai kebangkitan kesadaran Islam. Tahun-tahun itu ialah tahun-tahun awal dari apa yang sering disebut sebagai “revolusi jilbabâ€. Kota-kota besar sedang dilimpahi meningkatnya kesadaran beragama di kalangan terpelajarnya.
Di sekolah-sekolah menengah negeri favorit dan di kampus-kampus ternama para muslimah mulai mengenakan kerudung lebar yang menutupi kepala, leher hingga dada tersebut. Namun kesadaran tersebut mendapat tantangan keras. Diawali dengan SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 52/C/Kep/D/82 pada tahun 1982 tentang seragam sekolah di Sekolah Menengah. Peraturan tersebut tak memberi tempat yang cukup bagi jilbab untuk hadir di ruang pendidikan negeri. Peraturan itu kemudian diprotes oleh beberapa siswi SMA Negeri di Jakarta. Melalui Lembaga Studi Islam, mereka melayangkan surat ke sekolah-sekolah. Berharap pemakaian jilbab bagi siswi muslimah tidak mengalami hambatan dan tekanan.
Departemen P & K saat itu memberi reaksi atas peristiwa tersebut. Dalam siaran pers-nya, Pemerintah menyatakan siap membantu siswi berjilbab untuk pindah ke sekolah swasta. Pernyataan tersebut didukung oleh Mendikbud Nugroho Notosusanto, pada tahun 1984. Mendikbud memberi pernyataan singkat: "penting sekolah atau kerudung?". Berbagai hambatan tersebut justru menguatkan tekad sejumlah siswi berjilbab untuk mempertahankan keyakinannya. Pada tahun 1988, siswi berjilbab dari SMA 1 Bogor sempat menuntut kepala sekolah ganti rugi sebesar 100 juta Rupiah. Hal tersebut dikarenakan kepala sekolah tersebut mengeluarkan peraturan, siswi yang mengenakan jilbab ke sekolah dianggap tidak mengikuti pengajaran.
Persoalan jilbab terus mengemuka pada tahun selanjutnya. Sejumlah siswa SMA di Jakarta, Bogor, Purwokerto, Wonogiri, Surabaya, Ngawi, Sumatera Utara, Ujung Pandang, dan kota-kota lainnya "dikembalikan kepada orangtuanya" hanya karena mengenakan jilbab. Mereka sempat diusir, tidak boleh mengikuti pelajaran, diskors, dirumahkan, diteror, dikucilkan bahkan ada yang dikeluarkan dan akhirnya pindah ke sekolah swasta. Padahal mereka telah berusaha untuk “berseragam†sesuai aturan. Perbedaan pakain mereka dengan siswa yang tak berjilbab hanya terletak pada kemeja yang bertangan panjang, jilbab dan dan kaus kaki sepanjang lutut guna menutupi betis. Namun jilbab dipandang dengan cara politis, bukan pertimbangan agama, oleh pihak sekolah. Mereka yang berjilbab dicap sebagai orang-orang "ekstrim" yang perlu diwaspadai. Mereka juga dituduh bersikap eksklusif. Bahkan Kepala Sekolah SMA 6 Surabaya, menyamakan gerakan jilbab dengan gerakan PKI karena GTM (gerakan tutup mulut) dilakukan oleh siswi berjilbab di sekolahnya saat ditanya siapa ustadz mereka.
Berbagai upaya dilakukan para siswi untuk menjaga haknya sebagai muslimah. Mereka mengadu ke MUI, Mendikbud Fuad Hasan, dan LBH. 10 siswi SMA 68 menuntut agar keputusan Kepala Sekolah mengeluarkan siswi berjilbab dicabut. Gugatan melalui Direktur LBH Jakarta, Nursjahbani Katjasungkana, itu ditolak Pengadilan Tinggi. 70 siswi berjilbab SMA 1 dan 4 Bekasi menggelar demonstrasi ke kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada bulan Desember 1990, mengusung poster bertuliskan "kembalikan kami ke kelas tanpa lepas jilbab" dan "Jilbab Yes, Rok Mini No". Para muslimah muda ini terus bertahan dengan jilbabnya. Untuk mempertahankan jilbab, tak sedikit dari mereka yang harus mengundurkan diri dari sekolah negeri dan pindah ke sekolah swasta. Departemen Agama melalui Menterinya, Munawir Sjadzali, ternyata tidak mendukung masalah jilbab ini. Bahkan Menteri Agama menuduh pemikiran siswi-siswi itu kacau sebab dalam Qur'an tak ada ayat yang mewajibkan tentang jilbab.
Kondisi tersebut terus berlanjut sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing.
Selain di sekolah, dunia Perguruan Tinggi juga mengalami kasus serupa. Paling tidak hal ini dialami mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Permasalahan mahasiswi berbusana muslimah muncul ketika mereka mengikuti mata kuliah Human Need (semester IV) dan Praktika Klinika (semester V). Semua mahasiswi PSIK harus menggunakan pakaian seragam yang ditentukan Akademik. Seragam tersebut memustikan penanggalan jilbab. Awalnya peraturan ini tak bermasalah. Pada angkatan pertama, mahasiswi berkerudung hanya satu orang dan bersedia mengikuti ketentuan. Namun pada angkatan kedua (angkatan 86), mahasiswi berbusana muslimah tak dapat menerima ketentuan ini. Berbagai pertemuan dan pembicaraan diselenggarakan. Dekan FKUI Prof. Dr. Asri Rasad, Koordinator PSIK Achiryani Syuhaimi M.N., Dosen Agama, Dosen Pembimbing, perwakilan mahasiswi PSIK berjilbab melakukan beberapa pertemuan pada bulan Maret 1988. Hasilnya, ditetapkan pakaian seragam untuk mahasiswa berbusana muslimah dengan kriteria sebagai berikut: tutup kepala hitam dan cap seperti yang lain, lengan sampai siku dengan pertimbangan agar mudah cuci tangan, kerah tegak dan kaos kaki warna kulit. Pada tanggal 19 Maret 1988, mahasiswi berbusana muslimah dapat mengikuti praktika klinik dengan seragam yang telah disepakati itu.
Pada semester 5 (untuk mahasiswi angkatan 86) terdapat praktika klinik di Rumah Sakit. Masalah timbul sehubungan dengan penggunaan RS St. Carolus sebagai salah satu tempat praktek. RS St. Carolus tidak menerima mahasiswi PSIK-FKUI yang berseragam dengan tutup kepala. Hari-hari praktek terus berjalan. Lima mahasiswi yang tetap bertahan dengan seragamnya berupaya mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Dekan FK, Koordinator PSIK, FSI-FKUI, dan pengurus Masjid ARH UI sehingga mereka meninggalkan praktek sekitar dua minggu. Sayangnya, peraturan akademik menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak mengikuti praktek selama dua minggu berturut-turut dinyatakan bebas dari mata kuliah tersebut dan harus mengulanginya setahun kemudian. Ini artinya, kelulusan para muslimah tersebut harus tertunda. Setelah itu, mahasiswi berbusana muslimah diperbolehkan tidak praktek di RS St. Carolus oleh pihak pendidikan untuk tahun akademik 1989/1990.
Permasalahan di PSIK-FKUI kembali terjadi pada tahun 1991 karena mahasiswa berbusana muslimah diharuskan praktik klinika di R.S. St. Carolus dengan seragam sesuai dengan ketentuan. Serangkaian pertemuan diadakan kembali antara pihak akademik dengan mahasiswa pada bulan Januari sampai Mei 1991. Pihak akademik menghadirkan Dosen Agama YARSI yang tidak memberikan batasan aurat seperti yang diyakini mahasiswi. 12 orang mahasiswi tetap bertahan untuk memakai seragam praktek yang menutup kepala (ketika itu dikenal dengan “Jikonâ€= jilbab konde). Kata sepakat akhirnya dihasilkan, mahasiswi berbusana muslimah boleh tidak mengikuti praktek di RS St. Carolus cukup di RSCM.
Pada 16 Februari 1991, akhirnya terbit S.K. Dikdasmen No. 100/C/Kep/D/1991 yang mengatur pemakaian seragam khas sesuai dengan keyakinan peserta didik. Peraturan itu keluar atas desakan MUI yang juga telah mengadakan rangkaian pembicaraan dengan Depdikbud selama setahun. Selain itu berbagai protes dari siswi-siswi berjilbab yang jumlahnya terus bertambah tentu tak bisa diabaikan. Perjuangan bagi para muslimah untuk berbusana sesuai keyakinannya menemui titik terang.
Terbitnya S.K. Dikdasmen ini juga dijadikan momentum oleh para mahasiswi berjilbab FKUI untuk bernegosiasi kembali mengenai seragam praktik. Mereka mengajukan proposal disertai bukti-bukti ilmiah bahwa jilbab itu wajib, kebebasan beragama itu dilindungi UUD dan yang utama jilbab tidak mengganggu pelaksanaan kerja sebagai perawat di rumah sakit. Mereka merujuk pada al-Qur'an, UUD 45, GBHN, Sistem Kesehatan Nasional, S.K. Dikdasmen No. 100/C/Kep/D/1991, Fatwa MUI dan hasil observasi di beberapa rumah sakit Islam Jakarta. Proposal diterima pihak akademik.
Sejak tahun 1991 itu, mahasiswa berbusana muslimah memiliki seragam dengan jilbab bundar, baju lengan panjang dan celana panjang. Keberhasilan memperjuangkan pakaian seragam di PSIK-FKUI diikuti oleh akademi-akademi perawat lainnya seperti Akademi Perawat (Akper) Depkes, Akper R.S. Fatmawati dan berbagai Akper swasta lainnya. PSIK-FKUI menjadi pintu pembuka bagi kebebasan berekspresi mahasiswi di dalam dunia pendidikan tinggi.
Disadur dan disunting dari: Y. Setyo Hadi, “Jilbab: Simbol Kebangkitan Paham Islamisasi di Kampusâ€, dalam Masjid Arief Rahman Hakim Universitas Indonesia: Masjid Kampus untuk Ummat dan Bangsa (Lembaga Kajian Budaya Nusantara, Jakarta, 2000 hlm. 125-131)