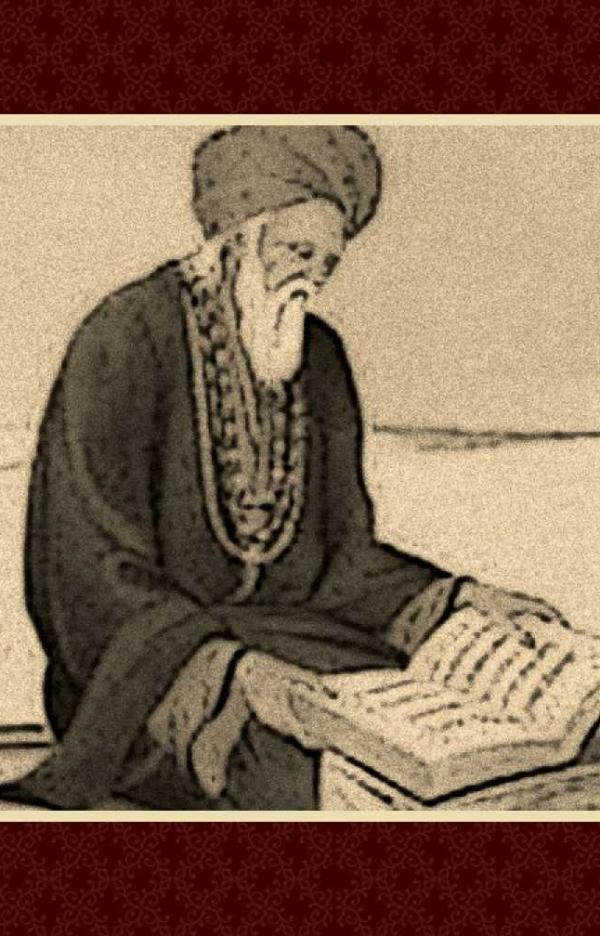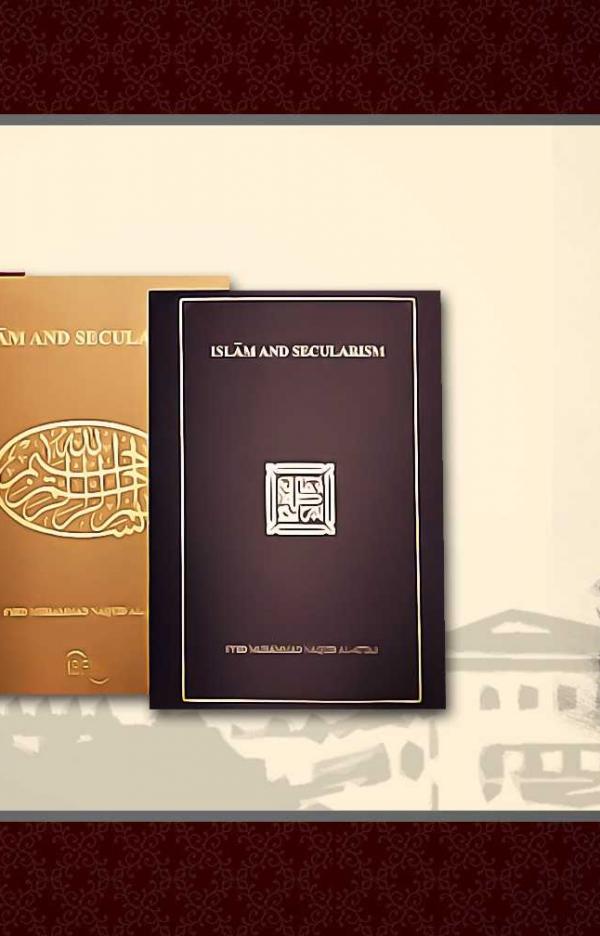Sebuah truk pasir memasuki pinggiran kota. Sopir truk melihat sekumpulan orang duduk di pinggir jalan. Mereka kuli-kuli bongkar muatan truk. Alat kerja mereka hanya sebuah sekop. Melihat truk mendekat, mereka berdiri dan siap mengadang. Sopir tak mengurangi kecepatan, cuma melambaikan tangan. Pertanda tidak butuh jasa bongkar para kuli. Rezeki para kuli lewat. Mereka duduk lagi menunggu truk berikutnya.
Tak berselang lama, truk lainnya mendekat. Para kuli berdiri lagi. Siap-siap mengadang. Kernet truk kasih isyarat jari tangan yang membentuk huruf V. Itu berarti truk butuh jasa dua kuli bongkar muatan truk. Sopir tetap memacu truk. Belasan kuli berebut mengejar truk yang berjalan cukup kencang.
Hanya empat kuli mampu mengejar truk. Kuli lain tercecer, tak mampu menandingi kecepatan truk. Empat kuli tersisa berebut naik bak truk, menggapai sisi kanan dan kiri truk. Tapi tiga kuli gagal naik bak truk. Mereka memilih turun. Seorang kuli masih bergelantungan di sisi bak truk. Satu tangannya mencengkeram batang kayu bak truk, tangan lainnya memegang sekop. Tubuhnya kelihatan limbung di sisi bak, nyaris jatuh. Tapi jari-jarinya begitu lengket dengan bak truk. Dengan sekali sentakan, dia berhasil masuk ke dalam bak bersama sekopnya.
Orang biasa boleh khawatir melihat kejadian tadi. Sebab, para kuli bisa jatuh dan terlindas ban besar kendaraan itu. Kalau benar kejadian, nyawa mereka bakal melayang. Tetapi, para kuli tenang-tenang saja menjalankan dan menyaksikan laku kerja berbahaya itu. “Ada yang telentang menatap langit, ada yang bersila sambil merokok, tapi tak jarang di antara mereka bersenda gurau.
Kebanyakan mereka berasal dari desa. Mereka kehilangan lahan pekerjaan. Sawah-sawah mereka menyempit sementara penduduk desa terus bertambah. Proses ini telah berlangsung dua abad yang lalu seperti ditulis oleh DH Burger dalam bukunya Sejarah Sosiologi Ekonomi Indonesia.
Sebagian mereka mempunyai keinginan pulang ke desa, bertemu keluarga di sana. Sementara, kuli lain keukeuh tinggal di kota. Umumnya, penempuh laku demikian ialah para kuli jejaka.
Sikap kuli-kuli terhadap desa boleh berbeda, tetapi sebagian besar mereka mempunyai tujuan sebangun: meningkatkan taraf hidup. Jerih payah mereka dari nguli hanya cukup untuk makan, minum, rokok, bekal sekadarnya bagi keluarga, dan sedikit berjudi. Malah saat truk lagi sepi, mereka tak beroleh apa-apa. Mesti menahan lapar. Ini tentu buruk, tetapi ada juga baiknya. Antara lain mereka terpaksa menahan diri dari berjudi.
Kuli-kuli itu tak sempat berpikir tentang hal lain di luar kebutuhan jasmani mereka. Tidak ada pikiran untuk menakar judi, tidak punya minat terhadap pendidikan. Shalat pun jarang.
“Islamnya mah Islam KTP,†gurau seorang kuli. Mereka hidup terpisah dari kelayakan dan kehormatan. Namun, terhadap merekalah umat Islam justru harus lebih menumpukan perhatiannya. Menjauhi mereka berarti melupakan ajaran Nabi Muhammad bahwa, “Tidak beriman seseorang kalau dia kenyang, sementara tetangganya lapar.â€
Demikian dikisahkan dalam di majalah Panji Masyarakat nomor 275, 15 Juli 1979, (hlm 39-40)
Denys Lombard, seorang bule pengepul sejarah Indonesia, pernah sepintas lalu melacak jejak kehadiran kuli-kuli semacam ini. Dia menyebut kehadiran kuli dari desa di kota sudah ada sejak masa perlawanan Diponegoro terhadap kuasa Belanda pada 1820-an. Kelompok kuli itu bernama batur.
Pangeran Diponegoro memberdayakan kuli-kuli untuk membantu perlawanannya. Kuli bertugas mengangkut dan menyambung pesan rahasia. Tetapi, seusai perlawanan Diponegoro, kuli-kuli itu enggan pulang ke desa. “... Menjelajah Jawa Tengah sebagai gerombolan liar,†tulis Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya 3, (halaman 157).
Pemerintah kolonial memandang batur sebagai penyakit sosial dan pengancam ketertiban. Kerja mereka saban hari ialah membuat orang-orang kaya Belanda hidup tanpa ketenangan dan minus kebahagiaan. Mereka menggondol harta kekayaan orang-orang kaya Belanda lalu memberikannya ke masyarakat papa.
Kuli-kuli bongkar muatan truk pada masa pembangunan memang tak sampai menjadi gerombolan liar. Mereka juga bukan penggondol harta orang kaya. Tetapi, keseharian mereka hampir mirip dengan para batur. Liar dan seenaknya. Tidur di mana pun dan berpakaian apa saja.
Dan mereka tetap bagian dari kita, seagama, sebangsa. Yang perlu kita cintai tentu bukan cuma mereka yang sekelompok sama kita. Mereka yang bergelimang dosa juga masih umat Islam. Perlu kita cintai juga. Sebab, umat Islam itu bukan cuma mereka yang ngaji bareng sama kita. Â
Sumber foto: Majalah Panji Masyarakat no 275, tanggal 15 Juli 1979, halaman 39.