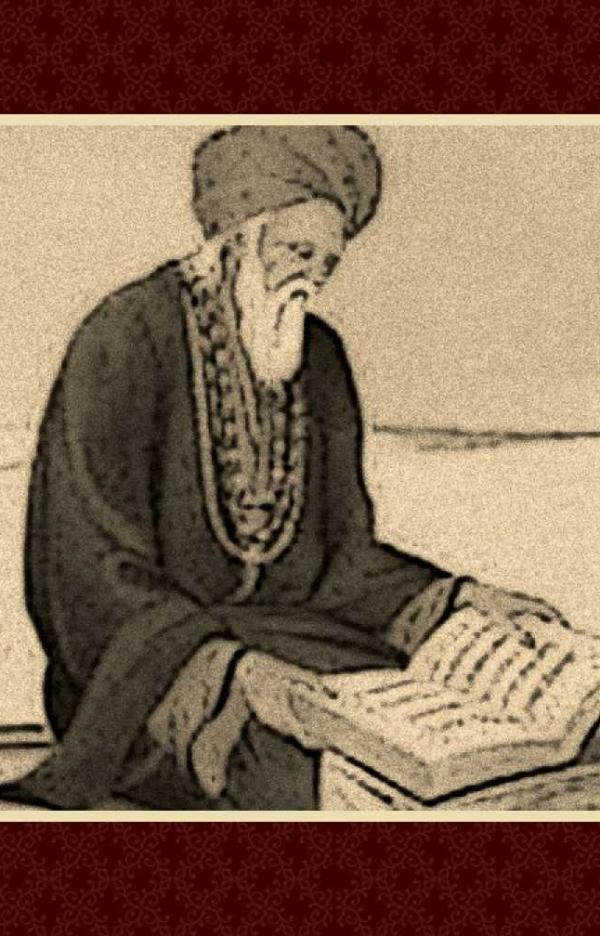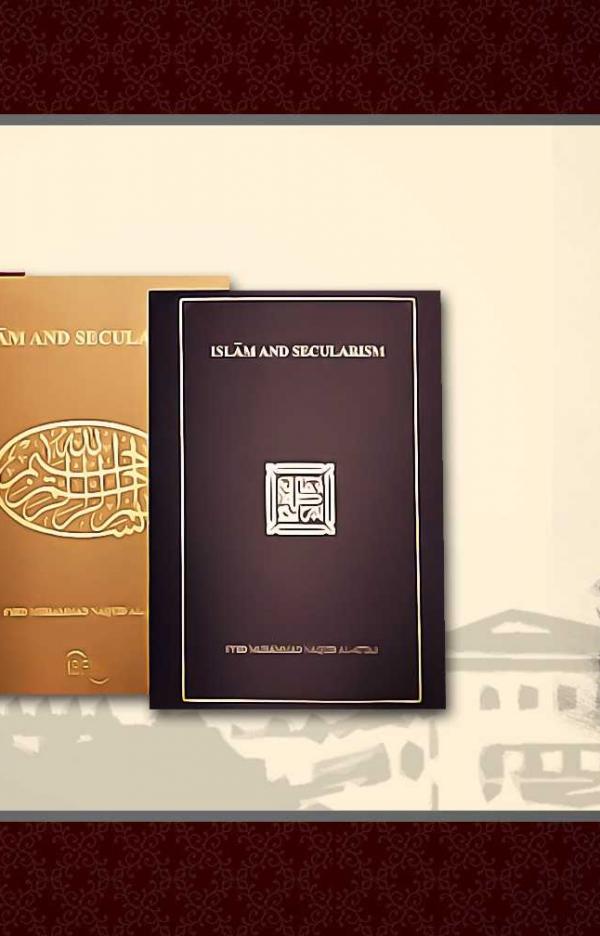Menonton Ikiru mengingatkan kita pada beberapa karya yang berbicara tentang hakikat hidup manusia, khususnya tentang kematian. Film ini berbicara tentang kesepian manusia di hadapan kematian dan takdir. Tema dan kecenderungan yang sama dapat kita temukan dalam Smert' Ivana Illicha (Matinya Ivan Illich [1886]), salah satu karya utama Leo Tolstoy (1828-1910). Akira Kurosawa bahkan secara jelas menyatakan karyanya ini terinspirasi dari cerita tentang Ivan Illich itu.
Ikiru boleh jadi bukan yang terbaik dari Kurosawa. Bagaimana pun Seven Samurai (1954) sering dirujuk sebagai karya terpenting sutradara kelahiran Shinagawa, 23 Maret 1910 ini. Namun dalam Ikiru lah pandangan terang Kurosawa mengenai kematian (dan juga kehidupan) dapat dengan jelas ditelusuri. Sekilas kita dapat menempatkan Kurosawa sebagai seorang eksistensialis yang memandang keterlukaan sebagai inti dari kehidupan. Senarai dengan laku seni Chairil Anwar di Indonesia atau penulis macam Leo Tolstoy dan Fyodor Dostoyevsky di Rusia yang sering menjadikan kemurungan sebagai titik balik pemerolehan elan vital kehidupan manusia. Orang-orang yang sering menjadikan ketragisan sebagai sesuatu kenyataan yang musti diterima, diakui dan disadari dalam kehidupan. Bahwa ketragisan ialah bagian utama dari kemanusiaan.
Tokoh Watanabe menjadi pencermin ketragisan tersebut. Diperankan secara apik oleh aktor langganan Kurosawa, Takashi Shimura, karakter Kanji Watanabe benar-benar berhasil menampilkan kegamangan, ketakberdayaan, absurditas dan ketragisan sekaligus gairah hidup manusia. Watanabe, seorang birokrat kawakan, pejabat yang memanggul-manggul kepalsuan sepanjang 30 tahun kariernya. Ia yang telah mati, menjadi mumi berjalan, ditelan segala kepura-puraan birokrasi yang menjengkelkan. Dalam pada itu, Watanabe yang tua berhadapan dengan kematian yang mengirimkan kecemasan melalui kanker perut.
Ia tak dapat mengadu dan berharap kepada siapa pun. Tidak kepada dokter, tidak kepada anaknya dan tidak pula kepada kedudukan yang selama ini ia bangga-banggakan. Kematian telah memisahkannya dari kenyataan, mengurungnya pada sebuah urusan pribadi yang terpisah dari orang lain. Tak ada pilihan, ia harus menghadapi dan menginsafi kematiannya secara sendirian. Dan dalam kesendirian itu ia mencoba mengurai makna hidupnya.
Kecemasan dapat membuat seseorang merasa sendirian atau keluar dari kehidupan sehari-hari yang didominasi oleh sesuatu yang tidak bermakna, begitu kata Karl Jeaspers. Lebih jauh, orang Jerman ini menyatakan bahwa manusia selalu berada, tak pernah terlepas, dari situasi-situasi yang mengitarinya. Sesuatu yang tak mungkin ditiadakan. Ini lah situasi batas, situasi yang tak mungkin dihindari oleh manusia. Dan situasi batas yang paling dramatis adalah kematian. Karenanya kematian ialah juga kesempurnaan kesadaran manusia atas keberadaannya. Kesadaran akan kematian akan mendorong manusia untuk hidup seasli-aslinya. Keinsafan terhadap kematian, sebuah keadaan yang tak mungkin terelakan sekaligus gelap dan tak dapat diketahui, akan melahirkan keberanian dan integritas.
Itu lah yang dialami Watanabe. Kecemasan menghadapi rupa-rupa masalah telah mengirimkannya pada kesunyian yang dalam. Ia tak berdaya, terpuruk dan putus asa. Ia seperti hendak tenggelam di sebuah kolam yang dingin dan sepi. Tangannya menggapai-gapai berharap seseorang akan menolong, tapi tak ada yang menolong, yang harus ia lakukan ialah menolong dirinya sendiri. Dan ia menyadari bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa, tak berdaya dalam menghadapi semua. Ia tak dapat menghentikan kematiannya, sebagaimana ia tak dapat berharap kesembuhan dari dokter yang tak pernah jujur.
Keadaan itu telah mendorong Watanabe untuk berlepas dari segala sesuatu di luar dirinya. Ia melepaskan segala tindakan palsu. Tindakan-tindakan yang dilakukan sekadar untuk memenuhi tuntutan sosial. Watanabe mencari-cari hakikat hidupnya, gairah hidupnya, yang bermakna dalam hidupnya. Kesadaran akan kematian, kesadaran akan absurditas masa lalunya telah melahirkan jiwanya yang baru.
Watanabe mengamuki hidupnya dengan pemberontakan terhadap segala yang nilai telah ia pegang teguh selama bertahun. Apa yang selama masa lalunya dianggap tak bermoral, ia lakukan. Ia tak masuk kantor, sesuatu yang tak pernah dilakukannya selama 30 tahun. Ia juga keluyuran malam, bersenang-senang, memboros, pergi ke tempat pelesiran dan minum sake mahal. Namun yang ia dapatkan dari laku memberontak itu hanya sunyi. Ia tak menemukan apa-apa dari amukan itu selain keheningan dan kehampaan hidup.
Sebagian besar pemikir sekular telah bersepakat bahwa hakikat itu tak ada. Kalau pun hakikat itu ada manusia tak akan dapat mencapainya. Yang terpenting bukan lah menemukan atau tak menemukan hakikat itu, namun yang terpenting ialah mencarinya terus menerus sepanjang hidup. Pencarian yang tak pernah (bahkan tak mungkin) selesai itu lah elan vital hidup yang sesungguhnya. Urusan manusia, menurut para pemikir eksistensialis, bukan untuk menemukan tetapi untuk terus melepaskan keyakinan dan terus melakukan pencarian.
Pada suatu ketika manusia akan keluar dari sebuah absurditas menuju kenyataan. Akan tetapi kenyataan itu kemudian akan menghablur menjadi absurditas yang lain. Dan manusia mencoba keluar darinya menggapai kenyataan lain yang selalu menjadi absurditas yang lain. Begitu terus menerus, sehingga Albert Camus mengisahkan perjuangan seorang Sisipus yang terus mendorong batu ke puncak gunung. Batu itu selalalu bergulir kembali ke bawah dan Sisipus harus mendorongnya kembali ke puncak. Sisipus memang telah dihukum dewa untuk selalu berlaku demikian dan ia tak dapat menghindarinya. Ia dikutuk untuk selalu berputar dalam kesia-siaa. Namun Sisipus (dalam pengisahan Camus) hanya tersenyum kecut pada hidup yang demikian. Tak perlu bergurau dengan hakikat. Menyadari bahwa ia harus selalu mendorong batu ke puncak telah cukup bagi batin Sisipus yang sepi.
Watanabe telah keluar dari keabsurdan hidupnya selama 30 tahun. Ia menanggalkan segala kepalsuan dalam kehidupan birokrasi yang penuh basa-basi dan kepura-puraan. Kesadaran akan kematian telah menyadarkannya bahwa ia tak berdaya. Dengan kesadaran ketakberdayaan itu ia menyambut kenyataan dirinya sebagai manusia yang bengal, memabuki hidup dan mencintai kesenangan. Akan tetapi yang ia dapat dari semua itu ialah keabsurdan yang lain. Kesenangan-kesenangan duniawi, kebebasan untuk memanjakan moral dan kedaulatan untuk melakukan sesuatu tanpa ketakutan atas pendapat dan pandangan orang lain hanya berujung pada kesunyian. Absurditas yang lain.
Lelaki ini kemudian mencari hal lain yang lebih otentik dalam hidupnya. Pada gadis Odagiri ia melihat gairah dan semangat hidup yang bebas dan berdaulat. Pertemuan Watanabe-Odagiri ini mirip dengan pertemuan Ivan Illich-Gerasim dalam karya Tolstoy. Kedaulatan dan kemurnian tak akan ditemukan dari sopan santun dan nilai yang terlepas jauh dari kejujuran. Seperti ajakan Nietzsche untuk tak menjadi harimau atau unta yang memangguli beban-beban nilai, melainkan menjadi anak kecil yang dengan riang mengguar keinginannya tanpa rasa bersalah. Maka dengan itu Watanabe menjalani apa yang berarti untuk hidupnya tanpa memerlukan penjelasan mengenai hakikat.
Lelaki tua itu mendamparkan sisa hidupnya pada pengabdian yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan orang banyak. Dengan segala ketakberdayaannya, dengan kesadarannya akan kematian, ia mencoba berbuat sesuatu. Kini keterlukaan itu tak lagi dihindari, hal itu diakui dan disadari sebagai bagian dari hidup. Keterlukaan dan hidup yang tragis telah mendorong Watanabe untuk melakukan semacam penebusan. Kesia-siaannya selama 30 tahun ia sudahi dengan semangat baru. Semangat mencipta yang bebas dan berdaulat.
Berbuat sesuatu yang baik tanpa peduli pada kebaikan itu sendiri. Watanabe mengabdi kepada manusia tanpa harus rikuh dengan pandangan manusia lainnya. Ia tak peduli ia akan disia-siakan, tak dianggap atau tak dihargai, yang ia tahu hanya bekerja dan berbuat baik. Watanabe telah menjadi skeptik pada nilai-nilai sosial yang melingkupi kantornya. Nilai-nilai yang menjemukan dan hampa. Ia bekerja di luar nilai-nilai itu. Yang ia lakukan begitu polos, lugu dan apa adanya.
Taman Kuroe adalam simbol dari tujuan yang tanpa beban. Watanabe mengerjakannya tanpa keinginan pada pujaan dan pujian. Tujuannya hanya taman itu sendiri. Bukan pangkat atau kemewahan lencana pekerjaan. Ia telah berhasil mengerjakan taman itu dengan gairah yang polos dan apa adanya. Di taman itu pula Watanabe menyambut kematiannya. Puncak absurditas dan ketragisan dari Ikiru. Seorang pahlawan yang tak dihargai secara wajar, tak dipahami lingkungan sosialnya dan berakhir di kematian yang sunyi. Ia telah menihilkan segala lakunya bagi dirinya sendiri. Jasanya dapat dinikmati orang lain, tapi ia sendiri tak dapat merasakannya karena telah tiada.
Film ini ialah sebuah cermin tamsil yang baik untuk menimbang dunia kita hari ini. Dunia yang semakin gandrung pada ketertataan, ketertiban, keruangan dan pengabdian. Dunia yang sedang gandrung untuk berbuat dan mengabdi. Upaya mengabdi yang dapat kita pandang sebagai penebusan atas dunia yang absurd. Atas laku koruptif dan segala macam ketakwarasan.
Taman-taman didirikan untuk menghibur kemanusiaan kita yang telah kalah digilas pengindustrian besar-besaran. Sarana-sarana umum dipoles indah menggapai-gapai kenyamanan demi menebus kesunyian manusia yang tertelan pergerakan kota yang amat cepat. Dan media sosial memanjakan kita untuk berpura bahagia, menebus segala luka yang kita simpan diam-diam di dalam kamar. Kita menebus yang pedih dengan senyuman seringan kapas di lautan mata yang memendam kepalsuan. Nihil, menghablur, pedih dan sunyi.
***
“Pada awalnya hidup itu sederhana, sampai perang, mesin industri dan Nietzsche membuatnya menjadi rumit†begitu ujar seorang kawan yang baru saja menenggak tetes terakhir kopinya.
Syaqawah (kesengsaraan) sesungguhnya ialah perkara batin. Mencari pembebasan atasnya dari perkara yang zahir tentulah kesia-siaan. Seseorang akan cemas, takut, khawatir pada sesuatu yang tak diketahuinya. Keyakinan bahwa diri tak mengetahui apa-apa dan tak mungkin mengetahui apa-apa ialah juga penyebab kesengsaraan. Pencarian dengan keyakinan tak akan pernah menemukan juga merupakan sumber kegundah-gulanaan.
Keyakinan dan pengetahuan yang memadai tentang diri dan Tuhan akan membuat seseorang menjalani hidup dengan nyaman. Kekecewaan, perasaan disingkirkan, patah hati, kesedihan, kepedihan, keterhimpitan nasib, duka lara dan segala kumpulan derita akan menjadi kenyataan yang terang. Bahwa semua itu ialah pendidikan Tuhan agar jiwa kita dapat menziarahi bermacam pesona rasa. Segala penderitaan duniawi akan tertunduk pada kesabaran dan ketawakalan. Juga kepasrahan akan kehadiran Tuhan. Setiap derita yang berlalu akan memberikan pelajaran. Dan jiwa yang telah menempuh bermacam rasa ialah jiwa yang sedia menerima berbagai macam coba. Ia menjadi lapang, luas dan mampu menanggung beban-beban. Jiwa yang lapang dan luas mampu pula untuk menanggung bermacam pengetahuan.
Tanpa Tuhan, hidup ialah kesia-siaan..,
Bahan Obrolan
Fuad Hasan, Berkenalan dengan Eksistensialisme (Jakarta: Pustaka Jaya, 1976).
Frederich Nietzsche, Sabda Zaratusta (Yogya: Quills Book Publisher, 2008).
Syed Muhammad Naquib al-Attas, IslÄm Faham Agama dan Asas Akhlak (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013).
Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ma’na Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam diterjemahkan dengan pengenalan dan nota penjelasan oleh Zainiy Uthman (Kuala Lumpur: ISTAC, 2002).
Thera Widyastuti, Konsep Kematian Menurut Eksistensialisme dalam Smert' Ivana Illicha Karya Leo Tolstoy, [Skripsi Jurusan Sastra Slavia, Program Studi Rusia] (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995).