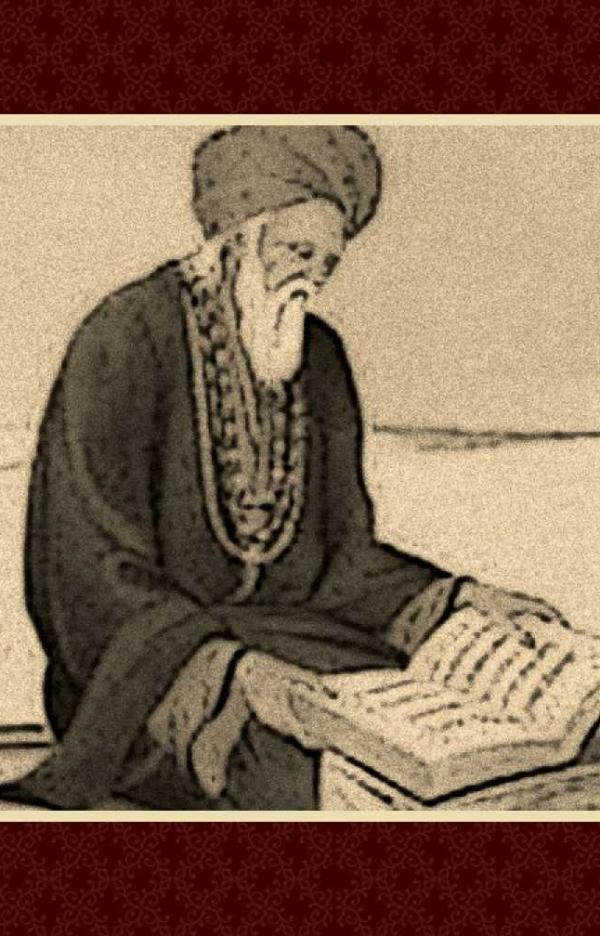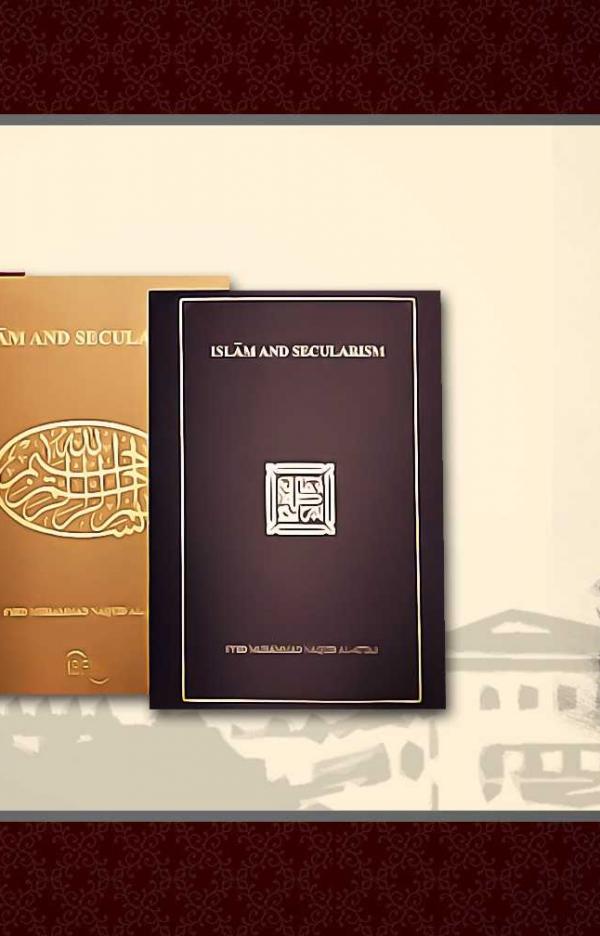Pada dasawarsa pertama abad ke-20, kekacauan di dalam kehidupan berkereta kita terjadi begitu marak. Tingkat kepadatan penumpang amat luar biasa. Sering kali jauh di atas kapasitas wajar kereta itu sendiri. Kita dapat melihat kereta rel listrik yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Bekasi, penumpang memenuhi seluruh bagian kereta. Bukan hanya di dalam gerbong-gerbong kereta, melainkan juga di atap, bordes, toilet bahkan ruang masinis. Di kepadatan tak manusiawi semacam itu, berseliweran para pedagang yang mendesak-desak minta jalan, berlalu lalang menjajakan dagangannya. Kadang ada yang menjual telur, salak, rambutan, apel, cabe merah, cutter, lem tikus, penambal panci, charger hp, panci sampai raket strum pembunuh nyamuk. Pengemis, jambret dan copet turut pula meramaikan kehidupan di dalam kereta. Tak lupa pula para pengamen dengan mantra mereka yang khas: “Ikhlas dari Anda, halal bagi kamiâ€.
Kondektur akan memeriksa karcis dengan sebuah alat khusus yang bunyinya khas. Tak semua penumpang membeli karcis, banyak juga yang menyogok kondektur di atas kereta. Lebih murah. Sogok menyogok terbuka nan radikal itu terjadi di muka umum dan diinsafi bersama. Kekacauan yang tak manusiawi tersebut telah membiasa dan orang-orang hidup dalam kekumuhan lahir batin itu selama bertahun-tahun. Tetes-tetes keringat di antara kesumpekan dan panas Jakarta yang keras ialah sarang bagi ketakteraturan.
Orang-orang kemudian menjadi baal dengan kekacauan yang kumuh itu. Sampah, bau pengap, ujaran-ujaran cabul, pertengkaran dan kata-kata kasar menjadi keseharian yang amat membiasa. Kereta menjadi sesuatu yang tak terlalu aman namun amat diperlukan. Orang-orang paling bawah menggunakannya untuk pergi mencari nafkah. Gerutuan selalu muncul, tetapi lebih sering berlalu begitu saja. Pada akhirnya kita melihat pelanggaran sebagai kewajaran. Semua seperti serba buntu dan tak ada jalan untuk mengakhirinya.
Namun, kemelataan yang tak manusiawi itu kemudian berakhir. PT. KAI mendirikan sebuah anak perusahaan bernama Kereta Commuter Line Jakarta (KCJ) pada 12 Agustus 2008. Beberapa perubahan penting dilakukan. Di antaranya penghapusan kelas kereta. Tak ada lagi kereta ekonomi atau eksekutif, tak ada pula Pakuan Ekspres. Semua kereta sama. Penertiban dan penataan di semua stasiun yang dilalui KRL terus dilakukan. Stasiun-stasiun KRL terus dipoles agar tampil lebih molek dan bergengsi. Perubahan lain yang juga penting ialah pemberlakuan tiket elektronik untuk menggunakan KRL.
Tak ada lagi pengemis, pengamen dan pengasong. Kekumuhan digusur, digantikan ketertataan ruang yang apik. Orang ramai-ramai memuji dan merasakan kenyamanan itu sebagai anugerah. Tata kelola KRL pada awal dasawarsa kedua abad ke-21 ini dianggap sebagai salah satu penataan yang mengubah kekumuhan kepada keberadaban.
Penataan semacam itu kadang terasa baik adanya. Meski kios-kios yang kumuh dan jorok harus digusur dan digantikan toko swalayan, toh orang-orang senang dan puas dengan kemajuan itu. Hasilnya dapat kita lihat dalam Laporan Tahunan PT. KJC 2015. Dengan jumlah 666 unit KRL dan 881 perjalanan setiap hari KRL telah mengangkut 257.530.195 penumpang sepanjang 2015 atau rata-rata 705.562 penumpang setiap hari. Dari 250 juta lebih penumpang tersebut, PT. KCJ memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 1,7 trilyun. Tak ada lagi uang yang menyangkut ke saku kondektur atau petugas penjaga pintu stasiun. Keduanya sudah tak ada lagi di KRL.
Angka-angka yang menyenangkan tentu saja. Laporan tahunan tersebut dibuat semanis mungkin dan dapat diperoleh oleh siapa saja. Ciri sebuah perusahaan yang terbuka. Peluang laku korup dari yang kecil-kecilan sampai yang gila-gilaan semakin sempit. PT. KCJ telah menghadirkan banyak harapan bagi perbaikan budaya bertransportasi kita.
Kita dapat melihat sebuah nilai baru dalam perubahan KRL tersebut. Suatu nilai yang dapat kita lihat dari sebuah peristiwa sekaligus laku: pintu stasiun.
***
Ketakteraturan telah dimulai di pintu stasiun. Orang-orang saling serobot di loket tiket, seperti tak tahu bagaimana cara berantri. Ada dua atau satu petugas keamanan yang menjaga pintu stasiun. Kadang mereka terlihat tegas, tapi kali lain sering nampak tak berdaya. Orang-orang tak berkarcis mendesak-desak, mengadu nyali dengan petugas. Yang tak terlalu bernyali, dapat mengepalkan barang 500 rupiah ke tangan penjaga pintu. Saku Sang Penjaga akan menggembung dengan uang sogokan. Sama seperti saku kondektur di atas gerbong kereta. Sementara para kenalan dapat masuk dengan percuma. Dan apabila seorang “tokoh†berlalu tanpa karcis, petugas akan sungkan untuk menegakkan peraturan. Orang-orang tak berkarcis berkeliaran dengan merdeka, bebas, leluasa dan semena-mena di pintu stasiun. Pedagang dengan tenang menyelundupkan barang dagangannya. Peraturan tak tegak, bahkan tak ada di kenyataan. Ia tertulis dan diumumkan, tapi hanya basa-basi.
Manusia bermacam watak menembus pintu stasiun, masuk beramai-ramai ke dalam tubuh kereta, kadang bergelantungan, persis seperti semut mengerubungi bangkai dengan serakah. Yang lemah dan yang kuat bersidesak, bersama yang baik dan yang jahat. Kereta berlalu dan datang. Di pintu stasiun yang tanpa peraturan itu, beribu-ribu manusia keluar masuk, nyaris seenaknya.
Debu kotor yang beterbangan menghiasi ribuan siang. Juga lantai yang kumuh dengan beragam pedagang yang menongkrong tanpa dosa di lorong-lorong. Asap rokok mengepul-ngepul dari banyak mulut tanpa empati, bersisahut dengan siulan iseng para lelaki. Di sudut yang agak tersebunyi, di belakang tembok stasiun, orang-orang yang baru turun dari kereta kencing tanpa sungkan. Mereka mampir buang hajat sebelum melanjutkan perjalanan.
Namun, pemandangan jorok semacam itu telah musnah dari 72 stasiun jalur KRL Jabodetabek hari ini. Tak ada sampah menumpuk, tak ada pedagang kusam di lorong-lorong stasiun. Tak ada lagi obrolan akrab para pengamen sebab pengamen telah tak ada di stasiun. Asap rokok telah dipojokkan di ruang-ruang terpencil yang tak nyaman. Tak ada gelandangan kumal, tak ada siulan iseng. Dan juga tak ada manusia yang berdiri memeriksa karcis di pintu stasiun.
Pintu stasiun kini telah dipalang dengan besi-besi kukuh. Tak ada jalan lain untuk membuka besi-besi itu selain dengan menempelkan sebuah kartu elektronik ke sebuah sensor. Preman, pedagang, polisi bahkan ustadz tak dapat menembus pintu itu kecuali dengan kartu tersebut. Semua orang, siapa pun dia, hanya dapat menembus pintu itu hanya dengan kartu elektronik itu. Melakukan pelanggaran berarti berhadapan dengan hukum. Dan besi tak dapat disogok atau menghormati, ia bekerja tanpa rasa dan pikiran.
Di pintu stasiun berpintu besi itu, semua manusia adalah sama. Setara. Ia tak melihat ustadz atau tentara, ia hanya dapat terbuka, apabila sistemnya bekerja. Tak perlu moralitas untuk masuk ke sebuah stasiun. Orang jahat, ahli maksiat, orang saleh, pemabuk, pengganja, pendeta, ustadz semua dapat masuk ke stasiun. Mereka yang berjilbab, mereka yang berpeci, mereka yang bercelana sangat pendek, mereka yang bertato atau mereka yang berpakaian ketat semua dapat melalui pintu stasiun. Asalkan memiliki kartu elektronik itu dan tak membawa duren yang baunya dapat mengganggu penumpang lain.
Mesin dan tata kelola serba otomatis yang melibatkan mesin-mesin yang tak dapat disogok memang dapat mendorong keteraturan. Sebuah tata aturan yang tak memerlukan peran agama, moralitas atau pembedaan pandangan terhadap manusia. Keteraturan itu memandang semua manusia secara sama rata. Tak ada yang istimewa. Manusia-manusia diatur seperti minuman kemasan yang berjejer di mesin-mesin pabrik. Tata ruang stasiun telah ditata sedemikian rupa sehingga setiap manusia akan melangkah nyaris dengan otomatis ke arah tujuan masing-masing. Seperti sebuah mesin yang dapat memilah kelapa yang kecil dan kelapa yang besar. Mengumpulkan berdasarkan kategori tertentu, ke arah tertentu dan kemudian mengemasnya.
Pola pengembangan keteraturan semacam ini telah menjadi gandrung dalam pembangunan di Indonesia. Online-isasi, besi-isasi, mesinisasi terus digalakkan bersama taman-taman artifisial, toko swalayan dan tempat makan cepat saji. Semua serba berseragam, teratur, nampak mahal, bergengsi dan tanpa banyak perbincangan. Semua berjalan bersama penyingkiran kios-kios yang susah diatur, preman-preman pelanggar aturan dan para pedagang yang tak tahu diuntung. Juga para kondektur dan penjaga pintu stasiun yang korup. Sistem ini telah menenggelamkan kekumuhan.
Pemesinan kehidupan terkadang dianggap cara yang ampuh untuk mengatasi sekian banyak keruwetan yang disebabkan oleh manusia. Di pintu stasiun, manusia yang dapat disogok telah digantikan palang besi yang tak dapat menyapa, tak berjiwa. Peran manusia semakin berkurang. Para penguasa amat gandrung membangun penataan banyak hal dengan cara macam ini. Kita kadang terhibur dengan musnahnya keruwetan-keruwetan. Kita kadang juga senang dengan taman-taman artifisial, toko swalayan dan tempat makan cepat saji. Namun kita juga patut mengingat, bahwa agama dan moralitas tidak diperlukan dalam penata-kelolaan semacam itu. Yang diperlukan hanya peraturan yang ditegakkan dengan tegas dan mesin yang bekerja dengan baik.
Tak heran apabila pemimpin-pemimpin semacam itu gemar berkampanye dan berceloteh soal pemisahan agama dan negara. Sebab pada akhirnya, mesin dan peraturan yang keras lah yang dapat mengeluarkan kita dari keruwetan. Bukan agama. Bahkan agama sendiri perlu diatur dengan tata cara sedemikian. Beragama harus sedapat mungkin menguntungkan negara. Begitu pikir mereka.
Kadang, kita umat Islam terpesona dengan perbaikan-perbaikan dan penataan yang kita anggap memberadabkan itu. Padahal kita semakin sedikit berbincang di ruang-ruang umum. Kita sudah jarang mengobrol di stasiun, asik dengan telepon genggam kita sendiri. Kita semakin tak peduli Bapak atau Ibu di samping kita hendak pergi ke mana. Kadang kita terlena dan terbuai dengan kepala daerah yang sedemikian. Atau presiden yang sedemikian. Mereka yang lebih percaya pada mesin daripada manusia. Mereka yang lebih percaya pada peraturan yang ketat dibandingkan kesadaran agama. Kita memang malas menelaah pikiran-pikiran halus disebalik lebih tertatanya sebuah pintu stasiun.
Kita menikmati keserba-teraturan yang mekanistik semacam itu. Seolah tak dapat membangun gagasan mengenai penata-kelolaan orang banyak dengan cara-cara yang lebih dekat dengan kemanusiaan kita. Kita juga lupa bahwa seorang Muslim yang senantiasa ingat akan Tuhannya, akan segan membuang sampah sembarangan. Ada atau tak ada petugas. Ada atau tak ada peraturan. Ada atau tak ada mesin. Seorang Muslim yang baik akan mengingat Tuhannya dalam setiap laku lampahnya. Dan seharusnya, itu menghasilkan keteraturan yang transendetal.