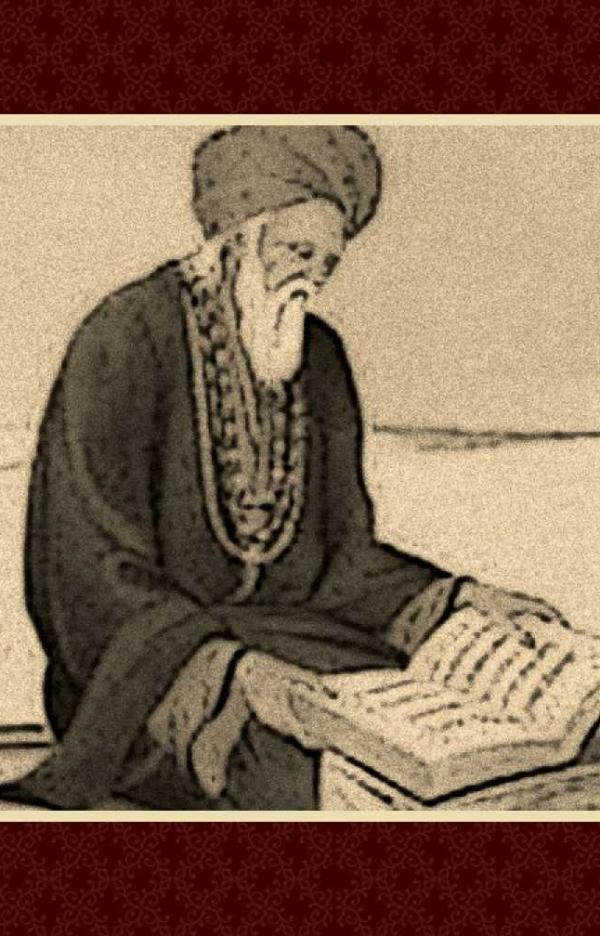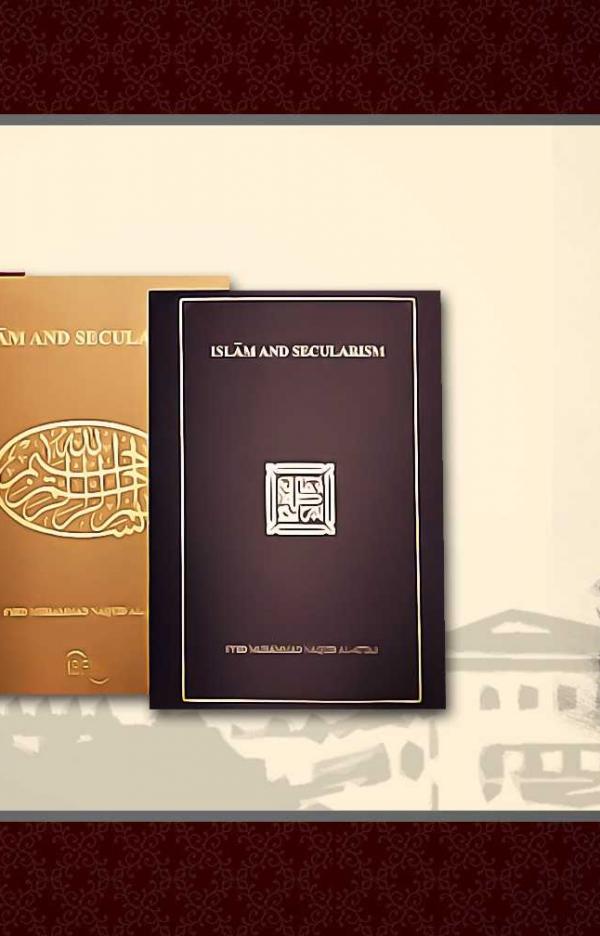Sekitar 13 atau 14 bulan yang lalu, sebagian pengguna media sosial di Indonesia meributkan beberapa soal matematika anak kelas II SD di Semarang. Seorang guru matematika menyatakan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 6= 24 adalah keliru. Artinya yang benar ialah 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4 = 24. Beributlah sebagian pengguna media sosial ketika itu.
Beberapa pihak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dua orang yang bergelar profesor (yang satu dalam bidang matematika dan yang lain dalam bidang fisika) turut serta memberikan pendapatnya. Pun banyak orang yang bukan profesor di bidang matematika dan fisika turut pula memberikan pandangan-pandangannya. Bahkan ada perdebatan panjang di sebuah status Facebook perkara soal di atas. Salah satunya seorang praktisi hukum yang berdebat dengan seorang wartawan, tentang matematika. Tentang 6 x 4 dan 4 x 6 itu.
Saya tidak hendak memperkeruh perdebatan yang sudah (seperti biasa) tampak dilupakan tersebut. Toh, sudah banyak urusan-urusan lain yang mengantre dan berderet untuk menjadi perdebatan lain. Namun, kisah “4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4 = 24†saya kira juga merupakan cermin masalah-masalah yang mengendap (dan mungkin tidak disadari oleh sebagian kita) yang terdapat dalam cara kita berpikir (atau cara berpikir kita?).
Ada banyak pendapat yang berseliweran tentang “4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4 = 24†itu. Salah satunya yang menyatakan begini: minum obat 3 kali 1 tablet itu berbeda dengan minum obat 1 kali 3 tablet. Dengan demikian, 3 x 1 dianggap tidak sama dengan 1 x 3. Juga ada pendapat yang menyatakan 4 keranjang berisi masing-masing 6 buah jeruk tidak sama dengan 6 keranjang berisi masing-masing berisi 4 buah jeruk. Juga pendapat-pendapat yang semirip dengan itu.
4 dan 6 yang tidak melibatkan jeruk, obat, keranjang, dan benda-benda lain yang terlihat mata tampaknya asing bagi kita. Untuk memahami 4 dan 6, kita merasa perlu melibatkan jeruk, obat, dan benda-benda lainnya. 4 dan 6 yang sendirian di alam berpikir “sana†dan tidak terlihat mata zahir tampaknya tidak terlibat dan dengan demikian tidak penting dalam keseharian kita. Mungkin kita mulai kehilangan kesadaran bahwa ada 4 dan 6, 3 dan 1, serta hal-hal lain yang terlepas dari benda-benda yang dianggap nyata. Bahwa 4, 6, 3, 1 dan lain-lainnya juga wujud.
Kita asing dari sesuatu yang tidak melibatkan jeruk, obat, atau benda-benda. Kita asing dengan sesuatu yang bukan benda dan terlepas dari benda-benda karena (mungkin) keseharian kita terlalu kental dengan hubungan dengan benda-benda. Kita asing dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, dan tidak bisa kita dengar. Sesuatu yang tak dapat dicerap oleh indra-indra lahir kita. Kita asing dan mungkin (jangan-jangan!) menganggap yang tidak benda itu tidak ada. Yang ada hanya yang benda saja.
Kita menganggap bahwa yang “ada†itu adalah “4 jeruk di dalam masing-masing 6 keranjangâ€, sedangkan “6 x 4†(atau “4 x 6â€) itu “tidak adaâ€. Atau paling tidak, “4 x 6†tidak lebih penting dari “6 jeruk di dalam masing-masing 4 keranjangâ€. Wujudkah “4 x 6†itu? Atau yang ada hanya “6 jeruk di dalam 4 keranjangâ€? Lalu, apa pentingnya mempersoalkan mana yang wujud dan mana yang tidak?
Yang Konkret dan Yang Tidak Konkret
Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat lema konkret dengan makna: nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya): contoh benda — adalah meja. Benarkah yang benar-benar ada (berwujud) adalah sesuatu yang semacam meja? Atau benarkah yang benar-benar ada itu ialah yang dapat dilihat, diraba, dan sebagainya?
Jawaban ini penting sebenarnya bagi kita. Akan tetapi, bisa jadi ini juga dianggap tidak lebih penting dari persoalan perebutan kekuasaan dan mendirikan bangunan-bangunan. Atau bahkan tidak penting sama sekali.
Saya sering mendapat ajakan-ajakan dari para politisi atau pelaku ekonomi, “Kita harus konkret!†Dan tampaknya yang dimaksud dengan konkret (benar-benar wujud, benar-benar ada) itu ialah yang memang dapat dicerap dengan indra lahir. Maka gerakan yang nyata ialah semacam gerakan ekonomi dan gerakan politik. Di luar itu tampak ditempatkan sebagai sesuatu yang mengawang-ngawang, tidak konkret, dan oleh karena itu dianggap juga sebagai tidak penting.
Berbondong-bondong orang mencoba melaksanakan tindakan yang (dianggap) konkret itu dalam macam-macam bidang. Yang konkret dalam berpolitik artinya mencari massa, melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk berkuasa dan kemudian menguasai wilayah tertentu. Yang konkret dalam ekonomi ialah mengumpulkan uang, membangun usaha, dan bersedekah.
Begitu pula yang dianggap konkret dalam pendidikan ialah mendirikan kelas-kelas, bangunan, atau sarana lain yang terlihat dan dianggap konkret (benar-benar ada). Pendidikan moral Pancasila mungkin dianggap kurang konkret, yang konkret adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun, tampaknya Pancasila juga masih dianggap mengawang-ngawang, yang konkret adalah kewarganegaraan. Yang konkret adalah hubungan warga dan negara. Moral? Tampaknya memakai helm dengan maksud agar tidak ditilang polisi lebih konkret daripada menggunakan sepeda motor dengan aman.
Lalu, bagaimana hubungan bangunan-bangunan penunjang pendidikan, uang-uang yang menumpuk dari hasil usaha, sedekah yang diulurkan, dan kekuasaan yang di dapat dari laku politik kita? Mana yang lebih penting? Mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita pentingkan?
Kita dapat melihat hubungan-hubungan itu dalam keadaan yang kacau. Orang-orang membangun kekuasaan. Orang-orang mendirikan sekolah dan bangunan-bangunan. Orang-orang berniaga. Sekolah tampak menjadi barang niaga, kuasa dijadikan penyokong usaha, dan para pengusaha menyogok para penguasa. Itu mewajar. Sewajar guru yang membagikan contekan pada ujian nasional. Membiasa. Sebiasa para pengusaha memberi “hadiah†kepada penguasa demi kelancaran usahanya.
Menata cara berpikir tampaknya ada di luar tata kekonkretan macam itu. Moral, nilai, persaudaraan, tenggang rasa, kejujuran, kejernihan, dan kemurnian tampak tidak konkret, tidak wujud dalam hubungan sekolah-sekolah yang diperdagangkan, usaha-usaha yang didirikan, dan juga kekuasaan yang diperebutkan.
Kita juga kebingungan untuk menghubungkan moral, kejujuran, dan nilai-nilai yang biasa disebutkan dalam sekian banyak ajaran itu dengan bangunan-bangunan, laku kuasa, dan perniagaan kita. Tampak ada jarak yang besar antara yang zahir dengan yang tak terindra. Antara “4 x 6†dengan “6 jeruk di dalam 4 keranjangâ€. Ketika kita kebingungan menghubungkan keduanya, kita lalu mempertentangkannya, menganggap yang satu lebih penting dari yang lain atau menganggap yang satu lebih konkret dibanding yang lain. Kita terjebak dalam kekeruhan itu, kemudian bingung melihat dan memahami apa yang sebenarnya benar-benar wujud, apa yang sebenarnya benar-benar ada.